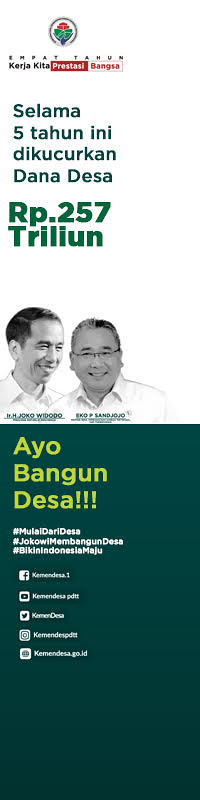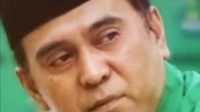Opini – Kerinduan akan kemerdekaan adalah cita-cita luhur yang muncul di setiap generasi bangsa yang terjajah. Semangat itulah yang membakar jiwa bangsa Indonesia sejak masa Kebangkitan Nasional tahun 1908 sebagai fase awal kebangkitan kolektif. Disusul oleh momentum Sumpah Pemuda tahun 1928, di mana para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara menyatakan persatuan dalam semangat Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa: Indonesia.
Tahun 1945 menjadi babak penting dalam sejarah bangsa. Di tengah situasi Perang Dunia II, ketika Jepang menjanjikan kemerdekaan, para pendiri bangsa dengan cerdas memanfaatkannya untuk memikirkan arah berdirinya negara. Di sinilah terjadi dialektika, diskusi dan perdebatan tentang bentuk negara dan Ideologi yang akan memayungi kehidupan bangsa yang merdeka. Bukan hal yang mudah, namun mengedepankan prinsip kesamaan nasib dalam penjajahan, sehingga diskusi itu berlangsung penuh heroik berhasil menemukan kesepakatan bersama.
Lahir dari semangat untuk keluar dari belenggu penjajahan, keterbelakangan, dan penindasa, para pendiri bangsa merumuskan nilai-nilai luhur sebagai penuntun hidup berbangsa dan bernegara. Tanggal 1 Juni 1945, dalam sidang BPUPKI, menjadi tonggak kelahiran Pancasila. Ir. Soekarno dengan jernih dan mendalam menyampaikan nilai-nilai yang telah hidup sejak zaman Sriwijaya dan Majapahit: lima sila yang integral, holistik, dan dinamis, yang kemudian kita kenal sebagai Pancasila.
Pancasila bukan sekadar rumusan politik, melainkan nilai hidup bangsa Indonesia. Menurut Soekarno, Pancasila dalah bintang penuntun (leitstar), bukan hanya untuk membentuk negara, tetapi juga untuk membentuk manusia dan masyarakat Indonesia yang seutuhnya. Menyatukan anak bangsa dalam kemajemukaan kultur, budaya, agama dan bahasa.
Namun kini, setelah Indonesia merdeka selama delapan dekade, Pancasila tampak kehilangan daya ikatnya. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap silanya semakin menjauh dari kenyataan hidup masyarakat. Pancasila hadir hanya sebagai simbol formal, teks dalam pembukaan UUD, dan hafalan di ruang kelas, tetapi teralienasi dari perbuatan nyata. Masyarakat Pancasila menjadi masyarakat yang terasing terhadap nilai-nilai Pancasila itu sendiri.
Paradox Nilai: Dari Sila ke Realita
Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, mengandung nilai ketaatan, religiusitas, dan kesadaran spiritual sebagai fondasi moral kehidupan. Namun hari ini, masyarakat kita makin lepas dari nilai-nilai transendental. Agama dijalankan lebih sebagai ritual kosong atau bahkan komoditas politik. Kebebasan tafsir yang tidak disertai tanggung jawab justru melahirkan liberalisme nilai, sekularisme sikap, dan formalisme ibadah. Akibatnya, jiwa menjadi kosong, dan agama kehilangan peran transformasionalnya.
Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, mengamanatkan kepekaan sosial, empati, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Tapi yang berkembang justru budaya Individualisme dan Pragmatisme. Norma, etika, dan adab dipinggirkan oleh kepentingan pribadi. Di ruang digital, kita menyaksikan setiap hari komentar dan ujaran kebencian, perundungan, dan kekerasan verbal menjadi hal biasa. Nilai adab tergerus oleh algoritma.
Sila ketiga, Persatuan Indonesia, yang seharusnya memperkuat kohesi sosial dan mengatasi sekat-sekat perbedaan, kini justru diuji oleh polarisasi identitas. Narasi kebangsaan tergantikan oleh fanatisme sempit, baik dalam politik, agama, maupun kelompok sosial. Gotong royong digantikan oleh kepentingan pribadi. Fakta meningkatnya kemiskinan, bunuh diri karena keputusasaan, dan apatisme sosial menunjukkan rapuhnya solidaritas kita sebagai bangsa.
Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, idealnya menciptakan proses demokrasi yang etis dan partisipatif. Namun dalam praktiknya, banyak keputusan publik diambil secara sepihak, tanpa musyawarah yang bermakna. Suara rakyat kecil tidak lagi menjadi pertimbangan, bahkan dalam sistem perwakilan. Musyawarah berubah menjadi formalitas, dan hikmat kebijaksanaan sering digantikan oleh logika kuasa.
Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, adalah puncak dari cita-cita Pancasila. Tapi realitas sosial justru menunjukkan ketimpangan yang dalam. Sebagian kecil menikmati kemewahan, sementara sebagian besar berjuang dalam ketidakpastian. Negara hadir, tapi tak selalu membela yang lemah. Keadilan menjadi cita-cita yang terus tertunda.
Modernitas dan Krisis Nilai
Kita tidak bisa menutup mata bahwa masyarakat modern membawa perubahan besar dalam pola pikir dan pola hidup. Rasionalitas, efisiensi, kebebasan individu, dan kecepatan menjadi nilai utama. Namun, modernitas tanpa nilai justru menciptakan kehampaan spiritual dan keterasingan moral. Kemajuan tidak selalu identik dengan peradaban, dan teknologi tidak otomatis melahirkan kemanusiaan.
Inilah tantangan besar masyarakat Pancasila: bagaimana tetap menjadi bangsa yang maju tanpa kehilangan jati diri. Bagaimana menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pegangan dalam menghadapi gempuran globalisasi dan arus nilai-nilai asing yang tidak selalu sejalan dengan karakter bangsa.
Penutup: Pancasila sebagai Jalan Hidup
Pancasila bukan sekadar ideologi negara. Ia adalah jalan hidup, ruh bangsa, dan dasar moral masyarakat Indonesia. Namun jalan ini tidak akan berarti tanpa kehadiran nilai-nilai itu dalam diri kita sebagai warga negara.
Hari Lahir Pancasila harus menjadi momentum reflektif, bukan seremonial. Kita harus bertanya: apakah kita masih hidup dalam semangat Pancasila? Ataukah kita telah menjadi masyarakat Pancasila yang teralienasi dari nilai-nilainya sendiri?
Inilah pekerjaan rumah kita bersama—membangunkan kembali nilai-nilai Pancasila, bukan hanya dalam wacana, tetapi dalam tindakan nyata. Agar bangsa ini tidak hanya besar karena sejarahnya, tapi juga kuat karena nilai-nilai yang dihidupinya.
Biografi Murni Parembai, SS.M.Ag
Penulis dilahirkan di Sidrap, 05 April 1974. Menyelesaikan Pendidikan S1, Fakultas Sastra Jurusan Asia Barat (1997) Kuliah rangkap Fakultas Agama Jurusan Tafsir Hadits di Universitas Muslim Indonesia Makassar Sulawesi Selatan. Tahun 1997-2000 melanjutkan S2 di Jurusan Magister Pengkajian Islam dengan Predikat Cumlaude. Tahun 2004 – sekarang penulis berkarir dan menetap di Jakarta. Sebagai Dosen tetap di Universitas Mohammad Husni Thamrin mengajar Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam di Fakultas Kesehatan Universitas Mohammad Husni Thamrin, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Mata Kuliah Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi Universitas MH.Thamrin. Penulis aktif di Organisasi ADPK Assosiasi Dosen Pendidikan Kewarganegaraan SeJabodetabek. Tahun 2014 mengikuti Training of trainer bagi Dosen ADPK di LEMHANAS. Aktif di FORNIKA (Forum Internalisasi Nilai-nilai Kebangsaan) alumni Lemhanas. Selain itu penulis juga mengajar Mata Kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Sekolah Kedinasan Politekhnis STIS Sekolah Tinggi Ilmu Statistik Otista Cawang Jakarta.
Penulis : Murni Parembai, SS.M.Ag