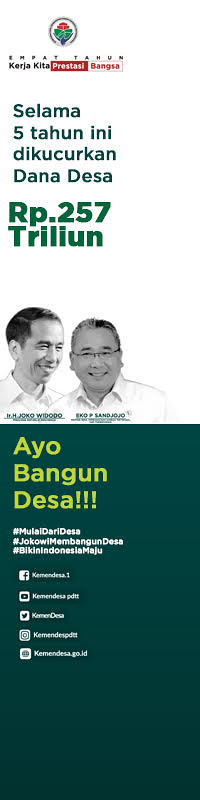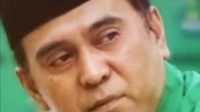Pulau Salemo di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) menjadi salah satu titik penting dalam sejarah dakwah Islam di kawasan pesisir Sulawesi Selatan. Di pulau kecil yang dikelilingi laut biru dan pasir putih itu, nama Puang Awalli , yang dikenal pula sebagai Syekh Abdul Rahim, menempati posisi sentral dalam memori keagamaan masyarakat. Ia bukan sekadar tokoh agama, tetapi simbol pertemuan antara spiritualitas Islam dan kearifan lokal masyarakat maritim. Cerita tentangnya tidak hanya hidup dalam kitab dan manuskrip, tetapi juga dalam tutur lisan, doa, dan ritual keagamaan yang diwariskan turun-temurun di Salemo.
Puang Awalli diyakini berasal dari keluarga ulama yang memiliki akar kuat di Wajo dan Gowa. Ayahnya, Afwan, berasal dari Wajo, sedangkan ibunya, Basse Tekong Daeng Kira, keturunan bangsawan Labakkang, Pangkep. Dari garis keturunan ini, tampak adanya sintesis budaya antara tradisi Bugis dan Makassar yang kelak memengaruhi corak dakwahnya. Ia menikah dengan Sayyana Daeng Jipa, keturunan dari Kerajaan Siang, yang memperluas jejaring sosial dan spiritualnya di kawasan pesisir barat Sulawesi Selatan. Pernikahan ini bukan hanya ikatan keluarga, melainkan juga jembatan dakwah yang menguatkan kedudukan agama Islam di tengah masyarakat pulau.
Menurut sumber lokal dan penelitian lapangan, Puang Awalli menempuh pendidikan agama di berbagai tempat, termasuk Mekkah. Dalam tradisi ulama abad ke-19 dan awal abad ke-20, perjalanan ke Tanah Suci bukan hanya untuk berhaji, tetapi juga untuk menimba ilmu syariah, tasawuf, dan tafsir. Di sana, ia diyakini berguru kepada sejumlah ulama Haramain dan membawa pulang pengetahuan yang luas tentang Islam klasik. Pengalaman ini memperkaya pemahamannya terhadap dimensi esoteris Islam, yang kelak menjadi dasar dalam pendekatan dakwahnya di Salemo — sebuah pendekatan yang lembut, simbolik, dan penuh makna spiritual.
Setibanya di Pulau Salemo, Puang Awalli menjadikan masjid sebagai pusat dakwah dan pendidikan. Masjid yang kini dikenal sebagai Masjid Nurul Ulama menjadi tempat pengajian kitab kuning dengan metode mangngaji tudang , yaitu tradisi mengaji duduk bersila, di mana guru membaca kitab dan menjelaskan maknanya, sementara santri menyimak dengan penuh takzim. Metode ini melahirkan generasi ulama pesisir yang tidak hanya memahami fikih dan tauhid, tetapi juga menghayati nilai-nilai sufistik. Pulau Salemo pun perlahan berkembang menjadi pusat pendidikan Islam tradisional yang disegani di wilayah kepulauan Spermonde.
Karisma Puang Awalli terletak pada kesederhanaan dan kedalaman spiritualnya. Masyarakat mengenangnya sebagai sosok yang dermawan, rendah hati, dan memiliki karamah. Cerita rakyat setempat menggambarkan bahwa laut di sekitar Salemo seolah tunduk padanya — kisah ini bukan untuk menuhankan manusia, melainkan untuk menunjukkan betapa kuatnya pengaruh spiritual seorang ulama yang dekat dengan Allah. Ia mampu mengharmonikan kehidupan religius dan realitas sosial nelayan, menjadikan agama bukan sekadar doktrin, tetapi juga jalan hidup yang menyatu dengan laut, angin, dan kerja keras.
Di masa hidupnya, pengajian Puang Awalli menarik murid-murid dari berbagai daerah. Mereka datang dari pulau-pulau lain di gugusan Spermonde, dari Liukang, bahkan dari daratan Sulawesi Selatan. Para santri tinggal sementara di Salemo, belajar membaca kitab kuning, mempelajari tata ibadah, dan memperdalam akhlak. Setelah selesai menimba ilmu, mereka kembali ke kampung halaman masing-masing, membawa ajaran gurunya dan mendirikan surau atau kelompok pengajian. Dengan cara inilah Islam tradisional menyebar ke berbagai pulau — bukan melalui ekspedisi besar, melainkan lewat jaringan guru dan murid yang berakar di komunitas pesisir.
Warisan Puang Awalli tidak hanya berupa pengetahuan agama, tetapi juga keteladanan moral. Ia menanamkan prinsip bahwa ilmu tidak boleh menjauh dari amal, dan ibadah tidak boleh terpisah dari kemanusiaan. Dalam setiap majelisnya, ia menekankan pentingnya kesabaran, kesantunan, dan keikhlasan dalam beragama. Nilai-nilai ini membuat ajarannya mudah diterima oleh masyarakat lokal yang masih memelihara adat dan sistem sosial berbasis kekerabatan. Islam yang diajarkannya adalah Islam yang merangkul, bukan memukul; mengajak, bukan menghakimi.
Setelah wafat, jasad Puang Awalli dimakamkan di sekitar kawasan Salemo, dan sebagian masyarakat meyakini makamnya juga terkait dengan Pulau Sabutun. Hingga kini, makam itu menjadi tempat ziarah dan penghormatan, terutama bagi warga yang ingin mengenang jasa ulama besar ini. Tradisi ziarah tidak hanya dimaknai sebagai pemujaan, melainkan sebagai penghormatan kepada orang saleh dan sebagai sarana refleksi spiritual. Di sana, orang berdoa, membaca tahlil, dan berharap berkah — sebuah praktik keagamaan yang mempertemukan dimensi sufistik dan sosial dalam satu ruang spiritualitas.
Secara historis, peranan Puang Awalli turut membentuk identitas keagamaan Pulau Salemo. Masyarakat setempat tetap memelihara tradisi keislaman yang berpadu dengan budaya lokal. Nilai-nilai seperti mappasereq (kebersamaan), sipakatau (memanusiakan sesama), dan pattudangeng (musyawarah) menjadi bagian integral dari kehidupan sosial dan keagamaan mereka. Dalam konteks inilah, warisan Puang Awalli tidak hanya menjadi kenangan spiritual, tetapi juga fondasi etika sosial masyarakat pulau yang terus bertahan menghadapi perubahan zaman.
Dari sudut pandang historiografi Islam Nusantara, jejak Puang Awalli di Salemo memperlihatkan bahwa penyebaran Islam tidak hanya dilakukan oleh kerajaan atau ekspedisi militer, melainkan juga oleh individu saleh yang hidup di tengah rakyat. Dakwahnya berlangsung secara damai dan kultural, melalui pendidikan, perkawinan, dan keteladanan. Ia menjadi bagian dari jaringan ulama pesisir yang menghubungkan pulau-pulau di Spermonde, sekaligus menunjukkan bagaimana Islam mampu beradaptasi dengan lingkungan maritim tanpa kehilangan substansinya.
Kini, seiring berkembangnya kajian tentang Islam lokal di Sulawesi Selatan, nama Puang Awalli mulai kembali mendapat perhatian. Peneliti dan akademisi mulai menelusuri naskah, silsilah, serta tradisi lisan yang terkait dengannya. Namun, masih banyak aspek yang perlu diteliti lebih lanjut, seperti kesinambungan ajarannya, peran keturunannya dalam pendidikan Islam, dan kemungkinan adanya dokumen tertulis peninggalannya. Dengan penelitian mendalam, sosok ini bisa ditempatkan secara lebih tepat dalam peta intelektual dan spiritual Islam kepulauan Indonesia.
Puang Awalli bukan sekadar nama dalam sejarah lokal, melainkan simbol dari model dakwah yang lembut, inklusif, dan berakar pada budaya. Di tengah arus globalisasi yang kerap mengikis nilai-nilai tradisional, kisahnya menjadi cermin tentang bagaimana agama dapat hidup berdampingan dengan adat, dan bagaimana ulama dapat menjadi jembatan antara langit dan laut, antara syariat dan kebijaksanaan lokal. Di Salemo, namanya terus disebut dalam doa — bukan hanya karena ia seorang wali, tetapi karena ia telah mengajarkan bagaimana menjadi manusia yang berilmu sekaligus beradab.
Daftar Pustaka
Abdurrahman, Dudung. (1999). Metodologi Penelitian Sejarah Islam. Yogyakarta: Tarawang Press.
Basri, Syarifuddin. (2020). Islam dan Tradisi Lokal di Sulawesi Selatan: Adaptasi dan Integrasi Nilai-Nilai Islam dalam Budaya Bugis-Makassar. Makassar: Alauddin University Press.
Firman, Muhammad Rafli. (2022). “Verifikasi Arah Kiblat Pemakaman Ulama di Pulau Salemo.” Skripsi. Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Alauddin Makassar. Repositori UIN Alauddin.
Latief, Hilmy. (2021). Ulama Pesisir dan Tradisi Islam di Sulawesi Selatan. Makassar: Balai Litbang Agama Makassar, Kementerian Agama RI.
Mattulada. (1985). Latoa: Suatu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis. Ujung Pandang: Hasanuddin University Press.
Rahim, Husain. (2018). “Dakwah Ulama di Kepulauan Spermonde: Studi Kasus Pulau Salemo dan Sabutung.” Jurnal Al-Qalam, Vol. 24, No. 2, 2018. Makassar: Balai Litbang Agama.
Rasyid, Abdul. (2019). “Mangngaji Tudang sebagai Tradisi Pendidikan Islam di Pulau Salemo.” Proceeding of the 2nd International Conference on Islamic Civilization and Local Wisdom (ICICLW), Atlantis Press. DOI:10.2991/iciclw-19.2019.3.
Said, Nurhayati. (2017). Pendidikan Islam Tradisional di Pulau-Pulau Sulawesi Selatan. Makassar: Alauddin University Press.
Salemo, Masyarakat Desa. (2020). Tradisi dan Kearifan Lokal Masyarakat Salemo dalam Menjaga Warisan Islam Pesisir. Pangkep: Pemerintah Desa Salemo.
Syam, Nur. (2010). Islam Pesisir dan Budaya Lokal. Yogyakarta: LKiS.
Oleh: Zaenuddin Endy
Koordinator LTN Imdadiyah JATMAN Sulawesi Selatan