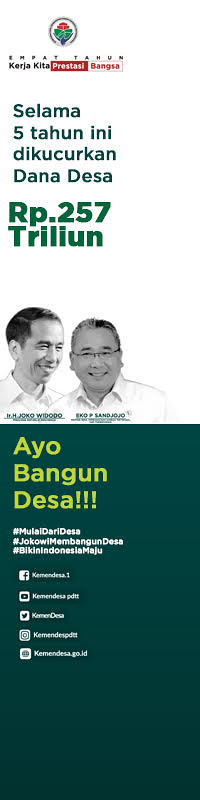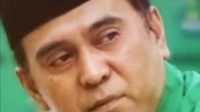Dalam khazanah tasawuf falsafi, konsep Martabat Tujuh menempati posisi yang sangat penting sebagai kerangka metafisis tentang penciptaan, hakikat wujud, dan perjalanan ruhani manusia menuju Tuhan. Ajaran ini berkembang pesat di dunia Islam melalui pemikiran para sufi besar seperti Ibn ‘Arabi, kemudian disistematisasi oleh al-Burhanpuri dalam al-Tuhfah al-Mursalah ila Ruh al-Nabi. Di Nusantara, konsep ini dihidupkan kembali oleh para ulama seperti Syekh Hamzah Fansuri dan Syamsuddin as-Sumatrani yang menjadikannya sebagai fondasi filsafat wujudiyah Melayu.
Martabat Tujuh menggambarkan tujuh tingkatan keberadaan Tuhan dalam relasinya dengan alam semesta. Ia merupakan upaya untuk menjelaskan bagaimana Dzat Mutlak yang tidak berhingga menampakkan diri-Nya dalam bentuk yang terbatas, tanpa kehilangan keesaan dan kesempurnaan-Nya. Setiap martabat merupakan tahap penyingkapan wujud, dari yang paling gaib dan mutlak hingga yang paling nyata dalam bentuk makhluk. Dengan demikian, ia bukan sekadar doktrin metafisika, tetapi juga jalan kontemplatif untuk memahami hubungan antara Tuhan dan ciptaan.
Tingkatan pertama disebut Ahadiyah, yakni martabat keesaan mutlak, di mana Tuhan belum dikenal dengan nama, sifat, atau perbuatan apa pun. Ia adalah wujud murni yang tak tersentuh oleh segala bentuk perbandingan. Pada martabat ini, tidak ada selain Allah; belum ada ‘alam’, belum ada makhluk, belum ada sesuatu pun selain kehadiran Dzat yang mutlak. Para sufi menggambarkan martabat ini sebagai “la ta‘ayyun” — tiada penampakan sama sekali.
Kemudian muncul Wahdah, martabat kedua, yakni kesatuan dalam kesadaran Dzat akan diri-Nya sendiri. Di sini, mulai tampak potensi untuk dikenal (ma‘rifah). Allah, dalam kebesaran-Nya, mengenal diri-Nya melalui nama-nama dan sifat-sifat-Nya. Namun, pada tahap ini, nama-nama dan sifat tersebut belum termanifestasi dalam realitas luar; ia masih berupa pengetahuan ilahiah yang menyatu dalam keesaan Dzat.
Tingkatan ketiga adalah Wahidiyah, tempat munculnya pengetahuan tentang makhluk secara potensial. Alam semesta belum tercipta secara nyata, tetapi semua hakikatnya telah berada dalam ilmu Allah. Dalam istilah sufi, tahap ini disebut ‘alam al-arwah — alam ruh, di mana segala kemungkinan wujud disimpan dalam pengetahuan Tuhan sebagai a‘yan tsabitah, yakni bentuk-bentuk hakiki yang tetap dalam ilmu-Nya.
Setelah itu muncullah Martabat Arwah, yaitu tahapan ketika ruh-ruh mulai diciptakan. Ini adalah manifestasi pertama dari ilmu Allah ke dalam bentuk yang dapat disebut “ada” secara simbolik. Pada tahap ini, ruh manusia, malaikat, dan seluruh makhluk halus berasal. Ia merupakan jembatan antara keghaiban murni dan kenyataan yang lebih konkret. Ruh adalah cahaya pertama yang menerima pancaran dari Nur Muhammad , sumber segala makhluk menurut pandangan wujudiyah.
Martabat kelima disebut Martabat Mitsal atau Martabat Alam Misal, yaitu alam bayangan atau bentuk halus. Ia merupakan ruang perantara antara ruh dan jasad, di mana makna-makna spiritual mulai mendapatkan bentuk simbolik. Alam ini menjadi medan tempat mimpi, ilham, dan visi ruhani terjadi. Di sini, bentuk-bentuk non-fisik memiliki eksistensi yang dapat dirasakan oleh kesadaran ruhani, bukan oleh pancaindra jasmani.
Tingkatan keenam adalah Martabat Ajsam, alam jasad atau materi. Pada tahap inilah manifestasi Tuhan mencapai bentuk konkret yang kita kenal sebagai alam semesta: langit, bumi, manusia, dan segala isinya. Ini adalah tahap terendah dalam skala emanasi wujud, tetapi justru menjadi tempat Tuhan dikenal secara paling jelas melalui tanda-tanda ciptaan-Nya. Alam materi adalah cermin bagi keindahan dan kekuasaan Ilahi.
Terakhir adalah Martabat Insan Kamil, puncak dari seluruh martabat. Pada tahap ini, manusia — khususnya insan kamil — menjadi mikrokosmos yang memantulkan seluruh aspek ketuhanan. Ia bukan Tuhan, tetapi bayangan sempurna dari-Nya. Dalam diri insan kamil, sifat-sifat ilahi menemukan cerminan paripurna. Karena itu, manusia dipandang sebagai tajalli terakhir dan termulia, tempat Tuhan menyaksikan diri-Nya sendiri dalam bentuk yang paling sempurna.
Konsep insan kamil ini memiliki dimensi etis dan spiritual yang sangat dalam. Ia mengajarkan bahwa tujuan hidup bukan sekadar keberadaan biologis, tetapi penyempurnaan diri agar mampu menjadi cermin bagi sifat-sifat Allah — seperti kasih sayang, keadilan, kebijaksanaan, dan keindahan. Dengan demikian, Martabat Tujuh bukan hanya teori metafisika, tetapi juga pedoman moral untuk menuju kesempurnaan ruhani.
Para sufi menafsirkan perjalanan spiritual manusia sebagai proses meniti kembali tujuh martabat tersebut. Manusia berasal dari Dzat yang Mutlak dan harus kembali kepada-Nya dengan kesadaran penuh. Proses ini dikenal sebagai as-sair ila Allah (perjalanan menuju Allah). Dalam perjalanan ini, seorang salik (pencari) harus melalui tahapan-tahapan fana dan baqa: melebur dalam kehadiran Tuhan dan kemudian hidup kembali dengan kesadaran Ilahi.
Dalam konteks keislaman Nusantara, ajaran Martabat Tujuh menjadi fondasi bagi banyak tarekat dan pemikiran sufistik. Hamzah Fansuri menggambarkan hakikat ini dalam syair-syairnya yang puitis, sementara Syamsuddin as-Sumatrani menjelaskan sistematika metafisisnya dalam kerangka yang lebih filosofis. Mereka tidak hanya mentransmisikan ide Ibn ‘Arabi, tetapi juga mengadaptasikannya dengan simbol dan bahasa lokal yang lebih mudah diterima masyarakat Melayu.
Namun, tidak semua ulama menerima ajaran ini tanpa kritik. Pada abad ke-17, Nuruddin ar-Raniri mengecam paham wujudiyah karena dianggap mendekati panteisme — menyamakan Tuhan dengan makhluk. Ia menilai bahwa pemahaman tersebut berpotensi mengaburkan batas antara Khaliq dan makhluk. Meski demikian, para penganut Martabat Tujuh menegaskan bahwa konsep mereka bukanlah penyamaan, tetapi penyingkapan relasi ontologis antara Yang Mutlak dan yang tampak.
Secara filosofis, Martabat Tujuh dapat dipahami sebagai model emanasi: dari Tuhan yang Esa terpancar realitas bertingkat yang semakin menurun tingkat kesempurnaannya. Namun, pancaran ini bukan berarti perpisahan, melainkan penyingkapan berlapis dari satu realitas tunggal. Dalam bahasa sufi, “tiada yang wujud selain Allah,” tetapi bukan berarti makhluk adalah Allah; melainkan makhluk adalah bayangan dari keberadaan-Nya yang mutlak.
Dalam kerangka ini, manusia memiliki kedudukan yang istimewa karena menjadi simpul pertemuan antara alam ruh dan alam jasad. Ia adalah miniatur alam semesta yang memuat seluruh tingkatan martabat dalam dirinya. Dengan menyadari hakikat dirinya, manusia dapat menempuh jalan kembali menuju sumber wujudnya. Kesadaran ini yang disebut ma‘rifah billah , pengetahuan langsung tentang Tuhan melalui pengalaman ruhani.
Ajaran Martabat Tujuh mengandung relevansi mendalam dalam konteks modern. Di tengah krisis spiritual dan materialisme yang menajam, ajaran ini menawarkan pandangan kosmologis yang menyatukan Tuhan, manusia, dan alam dalam satu kesatuan wujud yang harmonis. Ia mengajarkan keseimbangan antara dimensi transenden dan imanen, antara akal dan rasa, antara Tuhan yang jauh dan Tuhan yang dekat.
Selain itu, Martabat Tujuh juga dapat dibaca sebagai model epistemologi sufistik. Ia mengajarkan bahwa pengetahuan sejati tidak hanya diperoleh melalui rasio, tetapi melalui penyucian diri dan pengalaman batin yang mendalam. Pengetahuan tertinggi bukan tentang apa yang diketahui, tetapi tentang siapa yang mengetahui. Dalam kesadaran tertinggi, subjek dan objek pengetahuan melebur dalam satu kesatuan Ilahi.
Dalam tataran praksis, ajaran ini memotivasi manusia untuk mengintegrasikan dimensi spiritual ke dalam seluruh aspek kehidupan. Setiap tindakan, bila disadari sebagai pancaran kehendak Tuhan, menjadi ibadah yang memantulkan wujud Ilahi. Inilah makna “hidup bersama Allah” dalam segala keadaan — sebagaimana diajarkan oleh para wali dan mursyid tarekat.
Akhirnya, Martabat Tujuh mengajarkan bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan akan kembali kepada-Nya. Hidup adalah lingkaran wujud yang berawal dan berakhir dalam keesaan. Dalam kesadaran ini, manusia tidak lagi melihat perbedaan antara dunia dan akhirat, antara diri dan Tuhan, selain sebagai perbedaan cara pandang terhadap satu realitas yang sama. Kesempurnaan sejati terletak pada kemampuan melihat yang satu dalam yang banyak, dan yang banyak dalam yang satu.
Dengan demikian, Martabat Tujuh bukan sekadar sistem metafisika klasik, tetapi cermin dari pencarian spiritual manusia sepanjang zaman. Ia mengajarkan bahwa pengetahuan, cinta, dan kesadaran adalah jalan menuju Tuhan. Dalam keheningan hati, seorang salik akhirnya menyadari bahwa seluruh martabat itu bukanlah jarak, melainkan cermin yang menampakkan satu Wajah: Wujud Yang Maha Tunggal.
Daftar Pustaka
al-Burhanpuri, Muhammad ibn Fadl Allah. al-Tuhfah al-Mursalah ila Ruh al-Nabi. Hyderabad: Dairat al-Ma‘arif al-‘Uthmaniyyah, 1940.
al-Jili, ‘Abd al-Karim ibn Ibrahim. al-Insan al-Kamil fi Ma‘rifat al-Awakhir wa al-Awail. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997.
al-Qusyairi, Abu al-Qasim. al-Risalah al-Qusyairiyyah fi ‘Ilm al-Tashawwuf. Kairo: Dar al-Ma‘arif, 2001.
Ibn ‘Arabi, Muhyiddin. Futuhat al-Makkiyyah. Beirut: Dar Sadir, 1999.
Ibn ‘Arabi, Muhyiddin. Fusus al-Hikam. Diedit oleh Abu al-‘Ala ‘Afifi. Kairo: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1946.
Johns, A. H. The Gift Addressed to the Spirit of the Prophet: Study of the Tuhfat al-Mursalah of al-Burhanpuri. Canberra: Australian National University Press, 1965.
Nasr, Seyyed Hossein. Three Muslim Sages: Avicenna, Suhrawardi, Ibn ‘Arabi. Cambridge: Harvard University Press, 1964.
Nasution, Harun. Filsafat dan Mistisisme dalam Islam. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
Rais, Ahmad. Konsep Martabat Tujuh dalam Tasawuf Melayu-Nusantara: Kajian atas Pemikiran Syamsuddin as-Sumatrani. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2015.
Schimmel, Annemarie. Mystical Dimensions of Islam. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1975.
Simuh. Tasawuf dan Perkembangannya dalam Islam. Jakarta: Rajawali Pers, 1999.
Syamsuddin as-Sumatrani. Mir’at al-Muhaqqiqin. Aceh: Manuskrip Koleksi Dayah Tanoh Abee, n.d.
Syihabuddin al-Suhrawardi. Hikmat al-Isyraq. Teheran: Mu’assasah al-Mathbu‘at al-Islamiyyah, 1990.
Trimingham, J. Spencer. The Sufi Orders in Islam. Oxford: Clarendon Press, 1971.
Watt, W. Montgomery. Islamic Philosophy and Theology. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1985.
Yusuf, M. Amin. Martabat Tujuh dan Wujudiyah dalam Tasawuf Nusantara. Bandung: Mizan, 2009.
Zoetmulder, P. J. Pantheïsme dan Monisme dalam Sastra Suluk Jawa. Jakarta: Gramedia, 1995.
Oleh: Zaenuddin Endy
Koordinator LTN JATMAN Sulawesi Selatan