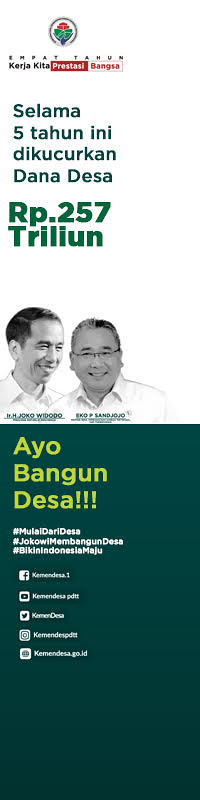Sejarah penyebaran Islam di Sulawesi Selatan tidak dapat dilepaskan dari peran para ulama perintis yang menanamkan dasar-dasar ajaran agama di berbagai kerajaan lokal. Salah satu sosok yang sering disebut dalam literatur sejarah adalah Laming, yang dikenal pula dengan sebutan Wali Pute. Nama ini merujuk kepada seorang muballigh dari Bone, tepatnya dari Pompanua, yang berperan penting dalam proses islamisasi Kerajaan Lamatti di Sinjai. Meskipun catatan mengenai dirinya tidak sebanyak tokoh besar lain seperti Datuk ri Bandang atau Dato’ ri Tiro, kehadirannya menandai jalur dakwah utara yang memperkuat posisi Islam di wilayah Tellu Limpoe.
Laming hadir pada masa di mana proses islamisasi sudah mulai diterima oleh sebagian kerajaan di sekitarnya. Kerajaan Gowa melalui dakwah Datuk ri Bandang dan kerajaan Tiro lewat peran Dato’ ri Tiro telah menjadi poros penting yang memperkenalkan Islam di selatan dan timur. Dari arah utara, Laming menjadi representasi Bone dalam proses penyebaran ajaran Islam, membawa misi dakwah yang bersinergi dengan gerakan dakwah dari poros lainnya. Posisi Bone yang strategis membuat lahirnya ulama seperti Laming tidak terlepas dari jaringan dakwah dan politik yang berkembang pada awal abad ke-17.
Konteks politik ketika itu memperlihatkan bahwa kerajaan-kerajaan di Sinjai, termasuk Lamatti, mulai terbuka menerima pengaruh luar. Setelah Raja Lamatti, Tuwa Suro, masuk Islam pada tahun 1613 melalui bimbingan Abdul Jawad Khatib Bungsu, maka ruang dakwah semakin luas untuk memperkuat ajaran Islam di tingkat rakyat. Laming datang setelah fase konversi elite ini berlangsung, sehingga peran utamanya lebih menekankan pada konsolidasi, penguatan, dan pelembagaan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat Lamatti. Inilah yang membuatnya berbeda dengan para muballigh awal yang menekankan konversi raja.
Kehadiran Laming juga memperlihatkan pola dakwah yang selaras dengan strategi “elite-first” dalam islamisasi di Nusantara. Dengan memantapkan posisi Islam di kerajaan Lamatti, ia memastikan bahwa perubahan keyakinan di tingkat elite diikuti dengan internalisasi ajaran di masyarakat luas. Pola ini terbukti efektif karena otoritas raja menjadi legitimasi yang memperlancar proses penerimaan Islam di kalangan rakyat. Dakwah Laming, karenanya, berada di persimpangan penting antara legitimasi politik dan penguatan religius.
Selain berdakwah, Laming diyakini memiliki peran dalam penguatan lembaga masjid dan literasi keagamaan. Tradisi panrita kitta atau orang-orang yang mampu membaca dan memahami kitab agama berkembang pesat di Sinjai setelah masuknya Islam. Situasi ini menunjukkan bahwa dakwah tidak berhenti pada pengislaman, melainkan bergerak menuju pendidikan keagamaan. Laming sebagai ulama dari Bone kemungkinan besar ikut serta dalam mentransfer pengetahuan dasar Islam kepada masyarakat Lamatti, memperluas jaringan ulama lokal, serta menumbuhkan tradisi baru dalam kehidupan sosial dan budaya.
Identitasnya sebagai Wali Pute—sosok berpakaian serba putih—memberikan simbol kesucian dan otoritas spiritual di mata masyarakat. Dalam tradisi Bugis-Makassar, pakaian putih sering dikaitkan dengan kesalehan, kebersihan jiwa, dan status religius. Dengan demikian, julukan ini bukan hanya sekadar sebutan, tetapi juga menegaskan karisma dakwah yang melekat pada dirinya. Keberadaannya tidak hanya dikenang dalam catatan tertulis, melainkan juga hidup dalam tradisi lisan masyarakat yang masih mengingatnya sebagai salah satu tokoh perintis Islam di kawasan itu.
Namun, perlu dicatat bahwa jejak fisik Laming tidak sejelas tokoh-tokoh lainnya. Hingga kini, tidak ditemukan makam atau situs yang secara pasti dikaitkan dengannya, baik di Bone maupun di Sinjai. Hal ini berbeda dengan sosok-sosok wali lain yang memiliki tempat ziarah. Ketiadaan bukti fisik membuat Laming lebih hidup dalam narasi sejarah dan tradisi lisan, tetapi justru di situlah terletak keunikan perannya: dakwahnya diingat bukan melalui monumen, melainkan melalui kesinambungan ajaran Islam yang bertahan di Lamatti hingga hari ini.
Keberadaan Laming juga sering kali disamakan dengan sosok lain yang populer di Pinrang, yaitu Pallipa Pute. Meski sama-sama dikenal dengan sebutan putih, keduanya sebenarnya berbeda konteks. Pallipa Pute memiliki makam di Katteong, Pinrang, dan dikenal luas dalam tradisi ziarah masyarakat setempat. Sementara itu, Laming atau Wali Pute adalah sosok muballigh dari Bone yang berdakwah di Lamatti. Pemisahan ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih narasi dalam studi sejarah islamisasi Sulawesi Selatan.
Dalam kerangka sejarah besar Islam di Sulawesi Selatan, peran Laming menegaskan bahwa islamisasi tidak hanya bergantung pada figur-figur besar yang sering ditulis ulang, tetapi juga pada tokoh-tokoh daerah yang bekerja di wilayah-wilayah tertentu. Dakwahnya menjadi mata rantai penting yang melengkapi narasi besar Islamisasi Bugis-Makassar, memperlihatkan bahwa proses penyebaran Islam merupakan hasil kerja kolektif banyak pihak, bukan semata jasa segelintir tokoh utama.
Dengan latar Bone yang memiliki tradisi kuat dalam dunia keulamaan, Laming menjadi simbol bagaimana daerah tersebut turut serta dalam proyek besar islamisasi Sulawesi Selatan. Ia bukan hanya representasi Bone di Lamatti, melainkan juga bukti bahwa jaringan ulama antarwilayah terjalin erat. Jaringan ini tidak hanya menyatukan kerajaan dalam agama baru, tetapi juga memperkuat identitas keagamaan regional yang bertahan hingga kini.
Bila ditinjau dengan teori difusi agama, peran Laming bisa dipahami sebagai bagian dari proses “consolidation of faith”, di mana dakwah bergerak dari elite ke masyarakat luas, lalu menumbuhkan pranata sosial-keagamaan. Inilah yang menjelaskan mengapa setelah era islamisasi, wilayah Sinjai dikenal sebagai salah satu pusat tumbuhnya literasi agama di Sulawesi Selatan. Dengan kata lain, kehadiran Laming berkontribusi pada lahirnya tradisi keilmuan Islam di Lamatti yang menjadi fondasi generasi ulama berikutnya.
Dalam perspektif historiografi Islam lokal, Laming memperlihatkan adanya ruang kosong yang masih perlu digali lebih dalam. Minimnya catatan biografis membuatnya sering hanya disebut sepintas dalam kajian akademik. Namun, justru karena itu, ia menawarkan tantangan bagi para peneliti untuk menelusuri lontaraq, manuskrip, maupun tradisi lisan di Bone dan Sinjai. Penelitian lanjutan berpotensi mengungkap identitas lengkap, jalur dakwah, serta pengaruh jangka panjangnya dalam kehidupan masyarakat setempat.
Dengan demikian, sosok Laming atau Wali Pute merupakan bagian dari mosaik islamisasi Sulawesi Selatan yang belum sepenuhnya terkuak. Ia adalah penghubung antara Bone dan Lamatti, sekaligus saksi atas bagaimana Islam diterima, dimantapkan, dan ditradisikan di tengah masyarakat Bugis. Meskipun jejak fisiknya samar, pengaruhnya tetap hidup dalam narasi sejarah, tradisi lisan, dan kesinambungan praktik keagamaan yang diwariskan hingga kini.
Laming menjadi bukti bahwa sejarah islamisasi bukan hanya tentang tokoh besar yang dikenang luas, tetapi juga tentang ulama-ulama daerah yang bekerja di lingkaran terbatas namun berpengaruh besar. Dengan menyelami kisahnya, kita diajak memahami bahwa islamisasi adalah sebuah proses panjang, kompleks, dan melibatkan banyak aktor. Dari Bone ke Lamatti, dari elite ke rakyat, dari simbol putih yang sakral ke kehidupan religius yang nyata—itulah jejak abadi Wali Pute yang terus terpatri dalam sejarah.
Oleh:Zaenuddin Endy
Founder Komunitas Pecinta Indonesia, Nusantara, dan Ulama (KOPI-NU)