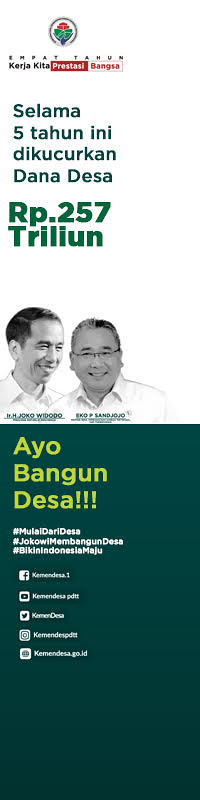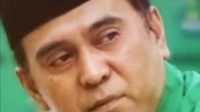Syekh Ahmad merupakan salah satu tokoh sentral dalam sejarah keulamaan Bugis, khususnya dalam struktur keagamaan Kerajaan Bone. Ia dikenal sebagai Petta Kalie ke-10, sebuah jabatan yang menandai otoritas keagamaan tertinggi dalam sistem kerajaan Islam Bone. Dalam konteks sosial-politik abad ke-19, peran Syekh Ahmad tidak hanya sebatas ulama yang mengurus urusan ibadah, tetapi juga sebagai pengawal nilai-nilai Islam dalam kebijakan kerajaan serta benteng moral dalam menghadapi tekanan kolonial. Kiprahnya memberikan warna yang sangat kuat dalam proses Islamisasi yang tidak hanya menyentuh sisi spiritual, tetapi juga melekat dalam struktur politik kerajaan.
Lahir dalam lingkungan keluarga bangsawan dan ulama, Syekh Ahmad mendapat pendidikan dasar agama dari pamannya, Haji Pesona, yang sebelumnya menjabat sebagai Petta Kalie Bone. Pendidikan tersebut membentuk fondasi keilmuan Islam yang kokoh dan memperkenalkannya pada jaringan ulama lokal yang berpadu dengan adat Bugis. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, ia melanjutkan studinya ke Mekkah selama kurang lebih empat tahun. Di tanah suci itu, Syekh Ahmad tidak hanya memperdalam ilmu fikih dan tasawuf, tetapi juga menjalin koneksi dengan jaringan ulama Hijaz yang memperkuat legitimasi keilmuannya sekembalinya ke tanah Bugis.
Setelah kembali dari Mekkah, Syekh Ahmad dipercaya untuk menggantikan pamannya sebagai Petta Kalie ke-10. Jabatan itu ia emban pada tahun 1823 M, bertepatan dengan naiknya Sultanah Salimah Rajiyatuddin sebagai Raja Bone ke-25. Selama masa pengabdiannya sebagai qadhi, Syekh Ahmad mendampingi tiga pemimpin kerajaan sekaligus, yakni Sultanah Salimah, Sultan Adam Najmuddin, dan Sultan Ahmad Shaleh Mahyuddin. Kepercayaan para raja tersebut menunjukkan pengaruh besar Syekh Ahmad dalam menjaga kesinambungan hukum Islam dan stabilitas kerajaan Bone di tengah dinamika perubahan sosial dan politik.
Syekh Ahmad bukan hanya ulama istana, tetapi juga guru dan pemimpin tarekat. Ia dikenal sebagai penganut tarekat Khalwatiyah Yusufiyah yang menjadi arus utama dalam spiritualitas Islam di Sulawesi Selatan pada waktu itu. Sebagai bagian dari komitmennya terhadap penyebaran ilmu, ia menyalin beberapa karya tasawuf, termasuk naskah-naskah karya Syekh Yusuf al-Makassari, yang menjadi referensi penting bagi ulama lokal. Penyalinan kitab tersebut menandakan kedalaman keilmuan Syekh Ahmad sekaligus dedikasinya dalam menyambungkan tradisi intelektual Islam Nusantara dengan pusat-pusat keilmuan Islam dunia.
Peran Syekh Ahmad sebagai Qadhi mencakup fungsi yudikatif, edukatif, dan moral. Ia menjadi pengawal pelaksanaan hukum Islam di wilayah kerajaan, sekaligus menjadi pembina masyarakat dalam urusan keagamaan. Dalam praktiknya, ia juga menjadi rujukan utama dalam fatwa-fatwa penting, termasuk dalam isu-isu politik yang melibatkan kekuasaan kolonial. Keberanian Syekh Ahmad dalam menghadapi kolonialisme menjadikannya sosok yang bukan hanya alim dalam ilmu, tetapi juga teguh dalam prinsip.
Salah satu momen penting dalam sejarah kepemimpinannya sebagai Qadhi adalah sikap tegasnya dalam menolak pembaharuan Perjanjian Bongaya yang diajukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Penolakannya bukanlah tindakan sporadis, melainkan bagian dari pemahaman keislaman dan kesetiaan pada martabat kerajaan Bone. Sikap ini juga memperlihatkan bahwa Syekh Ahmad memahami bahwa kolonialisme tidak hanya merampas tanah, tetapi juga mencabik-cabik otoritas budaya dan agama lokal. Karena itu, ia berdiri di garis depan bersama raja dan bangsawan Bone untuk mempertahankan kedaulatan mereka.
Akibat dari penolakan tersebut, Kerajaan Bone menjadi target serangan militer Belanda pada tahun 1825. Meski Bone berada dalam tekanan, Syekh Ahmad tidak mengendurkan perannya dalam membina masyarakat. Ia memperkuat lembaga keagamaan lokal, memperluas kegiatan pengajian, dan mendorong generasi muda untuk belajar Islam secara intensif. Keteguhan ini menjadikan Syekh Ahmad tidak hanya dihormati oleh istana, tetapi juga dicintai oleh masyarakat luas sebagai sosok ulama yang berani dan berpihak pada rakyat.
Dalam aspek pendidikan, Syekh Ahmad dikenal sebagai pengasuh halaqah ilmu di sekitar Masjid Al-Mujahidin Watampone. Masjid ini menjadi pusat kegiatan keagamaan dan intelektual Islam yang penting di Bone. Di tempat ini pula, Syekh Ahmad mendidik murid-muridnya dalam ilmu fikih, tasawuf, dan sejarah Islam. Tradisi pengajaran yang ia rintis diteruskan oleh para penerusnya dan menjadi cikal bakal pesantren dan madrasah lokal yang berkembang pada awal abad ke-20.
Syekh Ahmad juga memiliki perhatian besar terhadap pembinaan akhlak masyarakat. Dalam setiap khutbah dan pengajian, ia menekankan pentingnya kejujuran, tanggung jawab, dan cinta tanah air sebagai bagian dari ajaran Islam. Ia memadukan nilai-nilai keislaman dengan kearifan lokal Bugis, seperti pangadereng (tata nilai sosial) yang sarat dengan prinsip sipakatau, sipakainge, dan siri’ na pacce. Dengan pendekatan tersebut, Syekh Ahmad menjadi tokoh yang berhasil menjembatani antara nilai adat dan ajaran Islam tanpa menimbulkan resistensi sosial.
Masa pengabdiannya sebagai Qadhi berlangsung selama 24 tahun, menjadikan beliau sebagai salah satu Petta Kalie dengan masa jabatan terpanjang. Selama masa tersebut, Syekh Ahmad tidak pernah berkompromi dengan kekuasaan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan ketauhidan. Ia memanfaatkan jabatannya untuk mengawal masyarakat dalam menegakkan keimanan dan menjaga marwah kerajaan. Kiprah ini menjadikannya simbol integritas dan keberanian dalam sejarah ulama Bugis.
Pada tahun 1847 M, Syekh Ahmad wafat dalam usia yang matang dan dimakamkan di kompleks Masjid Al-Mujahidin, Watampone. Pemakaman itu menjadi simbol penghormatan tertinggi bagi seorang ulama kerajaan. Hingga kini, makam beliau masih diziarahi oleh masyarakat Bone dan menjadi titik penting dalam napak tilas sejarah Islam lokal. Kepergian Syekh Ahmad menandai akhir dari satu era kepemimpinan qadhi yang penuh integritas, namun warisannya tetap hidup melalui generasi murid dan lembaga keagamaan yang ditinggalkannya.
Setelah wafatnya, jabatan Qadhi dilanjutkan oleh sepupunya, KH. Adam, yang juga pernah menuntut ilmu bersama Syekh Ahmad di Mekkah. Hal ini memperlihatkan adanya kesinambungan kaderisasi ulama yang kuat dalam struktur keulamaan Bone. Tradisi pengangkatan Qadhi dari kalangan yang terdidik secara mendalam dalam Islam menjadi ciri khas kerajaan Bone dalam mempertahankan kualitas keagamaannya.
Syekh Ahmad bukan hanya Qadhi dalam arti legal-formal, tetapi juga pemimpin spiritual dan intelektual yang menjadi poros integrasi antara agama, budaya, dan politik. Ia menunjukkan bahwa seorang ulama tidak hanya harus menguasai kitab, tetapi juga berani mengambil sikap ketika agama dan umat berada dalam ancaman. Sosoknya merupakan representasi ulama yang memahami zaman, berakar dalam tradisi, dan terbuka terhadap ilmu.
Dalam perspektif akademik, Syekh Ahmad dapat dikaji lebih jauh sebagai contoh model ulama negarawan (al-‘alim al-mujtama’i) yang memainkan peran strategis dalam menjaga kohesi sosial. Ia juga menjadi bukti bagaimana Islam tumbuh dalam konteks lokal dengan mengakar pada budaya setempat tanpa kehilangan substansi ajaran universalnya. Penelitian terhadap peran Syekh Ahmad menjadi penting untuk memahami sejarah Islam lokal sebagai bagian dari narasi besar keislaman Nusantara.
Kisah hidup Syekh Ahmad menyimpan banyak pelajaran tentang keteladanan, keberanian, dan komitmen pada keilmuan. Dalam situasi bangsa yang menghadapi tantangan moral dan spiritual, figur seperti beliau perlu diangkat kembali sebagai inspirasi publik. Dengan menelusuri jejak Syekh Ahmad, kita tidak hanya melihat masa lalu, tetapi juga memperoleh cermin bagi masa depan keulamaan yang berakar dan berdaya tahan terhadap zaman.
Oleh: Zaenuddin Endy
Komunitas Pecinta Indonesia dan Nusantara (KOPI-NU)