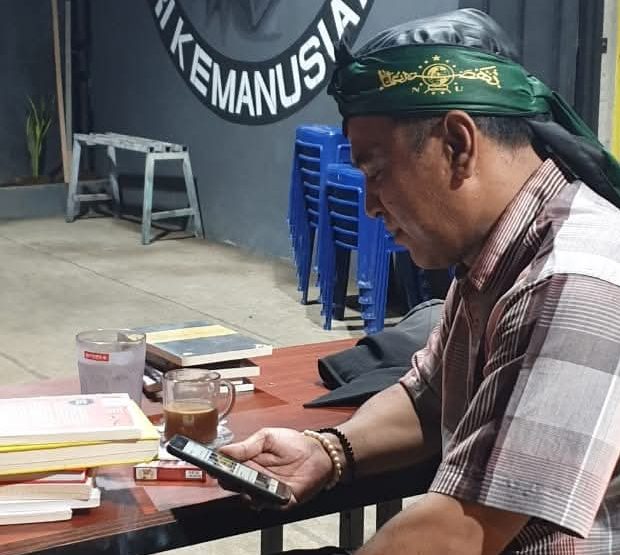Kekisruhan yang sempat mengemuka di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan kemudian berakhir dengan guyub secara organisasi adalah sebuah fenomena yang, meski tampak damai di permukaan, tidak serta-merta layak dijadikan contoh oleh organisasi lain. Apa yang terjadi di NU memiliki konteks historis, kultural, dan sosiologis yang sangat khas, sehingga tidak bisa disederhanakan sebagai model resolusi konflik universal.
NU bukan sekadar organisasi modern dengan struktur administratif formal. Ia adalah pertautan antara jam’iyyah diniyyah, jaringan kiai, tradisi pesantren, serta relasi kultural yang hidup dan berlapis. Karena itu, dinamika internal NU sering kali bergerak dengan logika yang tidak sepenuhnya bisa dibaca melalui kacamata manajemen organisasi konvensional.
Ketika kekisruhan muncul di PBNU, publik sering kali menilainya dengan standar organisasi rasional-modern: ada konflik, ada kegaduhan, ada perbedaan sikap elite. Namun, cara NU mengelola ketegangan itu sering kali tidak berjalan melalui mekanisme formal yang kasat mata, melainkan melalui kanal-kanal informal berbasis etika, sanad keilmuan, dan penghormatan simbolik terhadap otoritas keagamaan.
Berakhirnya kekisruhan dengan suasana guyub tidak boleh dibaca sebagai legitimasi bahwa konflik terbuka adalah sesuatu yang aman untuk dipertontonkan. Justru di sinilah letak bahayanya jika organisasi lain meniru fenomena tersebut tanpa memiliki “modal kultural” sebagaimana NU. Tidak semua organisasi memiliki cadangan moral dan kepercayaan kolektif yang cukup untuk meredam luka pasca-konflik.
NU memiliki sejarah panjang dalam mengelola perbedaan, bahkan sejak masa awal berdirinya. Tradisi bahtsul masail, ikhtilaf fiqhiyyah, dan perbedaan ijtihad telah membentuk budaya internal yang relatif matang dalam menghadapi silang pendapat. Namun, kematangan itu lahir dari proses historis yang panjang, bukan dari improvisasi sesaat.
Dalam konteks PBNU, kekisruhan yang berakhir dengan harmoni lebih tepat dipahami sebagai pengecualian yang lahir dari karakter organisasi, bukan sebagai kaidah umum. Jika ditiru secara serampangan, justru berpotensi merusak sendi organisasi lain yang belum memiliki ketahanan internal serupa.
Fenomena ini sekaligus menegaskan bahwa NU adalah organisasi yang sulit ditebak. Ketidak-tertebakan itu bukan karena chaos, melainkan karena NU digerakkan oleh logika jam’iyyah yang sering kali melampaui kalkulasi politik jangka pendek dan nalar administratif semata. Ada dimensi etik dan spiritual yang bekerja di balik layar.
Bagi publik luar, NU mungkin tampak paradoksal: keras dalam perbedaan, tetapi lembut dalam penyelesaian; riuh dalam dinamika, tetapi teduh dalam keputusan akhir. Paradoks inilah yang membuat NU sering kali mengejutkan, bahkan bagi kadernya sendiri.
Namun, perlu ditegaskan bahwa ketaktertebakan NU bukanlah sesuatu yang ideal untuk direplikasi. Organisasi lain yang mencoba “berisik dulu lalu berdamai belakangan” tanpa fondasi nilai yang kuat justru berisiko terjebak dalam konflik berkepanjangan yang destruktif.
Guyubnya NU pasca-kekisruhan tidak lahir dari kompromi pragmatis belaka, melainkan dari kesadaran kolektif tentang bahaya konflik berkepanjangan bagi umat. Kesadaran ini ditopang oleh otoritas moral kiai dan tradisi ta’dzim yang masih relatif kuat.
Di titik inilah, kekisruhan PBNU seharusnya dibaca sebagai pelajaran tentang keunikan, bukan tentang prosedur. Ia menunjukkan bahwa NU memiliki mekanisme internal yang tidak selalu rasional secara struktural, tetapi efektif secara kultural.
Organisasi lain yang tidak memiliki jaringan nilai serupa sebaiknya belajar pada prinsip dasarnya, bukan pada gejala luarnya. Prinsip itu adalah kedewasaan dalam berbeda, kesediaan untuk menahan ego, dan kemampuan mendahulukan maslahat bersama.
Jika hanya meniru bentuk luarnya, kekisruhan yang dibiarkan lalu diredam, tanpa membangun fondasi etik dan budaya dialog, yang terjadi bukanlah guyub, melainkan fragmentasi.
Karena itu, kekisruhan PBNU tidak layak dijadikan justifikasi bahwa konflik terbuka selalu bisa diakhiri dengan damai. Ia adalah cermin bahwa NU bekerja dengan logika yang khas, sering kali tak terduga, dan tidak selalu bisa dijelaskan dengan teori organisasi modern.
NU adalah organisasi yang hidup dari tradisi, bukan sekadar prosedur. Ia bergerak dari nilai, bukan hanya aturan. Ketika nilai itu masih kuat, konflik bisa dikelola; ketika nilai itu rapuh, konflik bisa menjadi bencana.
Fenomena ini mengingatkan bahwa NU memang organisasi yang tidak bisa ditebak, tetapi justru karena itulah ia bertahan. Ketaktertebakan itu adalah hasil dari kedalaman sejarah dan kearifan kolektif, bukan dari romantisasi kekisruhan yang patut ditiru oleh siapa pun.
Oleh: Zaenuddin Endy
Komunitas Pecinta Indonesia, Nusantara, dan Ulama (KOPINU)