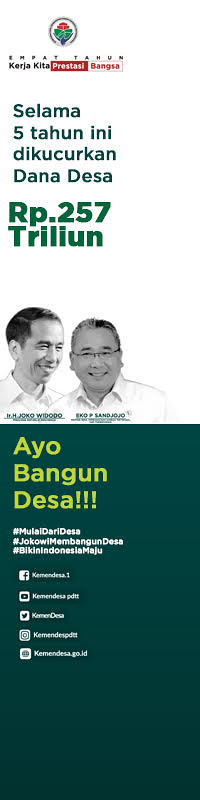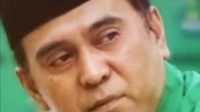Islam hadir ke berbagai belahan dunia bukan sebagai badai yang merobohkan rumah tua, melainkan sebagai cahaya yang menyalakan kembali ruang-ruang hikmah yang sudah lama dibangun oleh para leluhur. Di banyak tempat, termasuk Nusantara, ajaran Islam tidak datang dengan niat merusak akar kebudayaan, tetapi justru menumbuhkan tunas baru yang tumbuh harmonis dari batang tradisi yang sudah mengakar kuat. Itulah mengapa di banyak desa kuno, orang bisa melihat masjid berdampingan dengan rumah adat tanpa rasa saling menghapus. Ada harmoni yang lahir dari perjumpaan itu.
Ketika Islam tiba, para pembawa risalahnya membaca realitas budaya dengan mata yang lembut. Mereka tidak memulai dakwah dengan vonis, melainkan dengan memahami apa yang dimuliakan oleh masyarakat setempat. Tradisi, adat, dan simbol-simbol lokal tidak disapu sebagai kesalahan, tetapi dipilah mana yang selaras dengan tauhid dan mana yang hanya butuh penyempurnaan. Cara ini membuat masyarakat merasa dihargai, bukan dihakimi, sehingga ajaran Islam tumbuh sebagai bagian dari kehidupan mereka, bukan sebagai kekuatan asing yang memaksa.
Leluhur di banyak daerah telah memegang nilai-nilai universal seperti gotong royong, kesetiaan, bakti kepada orang tua, dan penghormatan terhadap alam. Ketika Islam datang, nilai-nilai ini tidak dianggap sebagai kompetitor wahyu. Sebaliknya, nilai-nilai itu diperkuat, diberi fondasi spiritual, dan diarahkan pada tujuan yang lebih luas. Gotong royong misalnya, dipertemukan dengan ajaran taawun. Sikap hormat kepada orang tua terjalin erat dengan perintah birrul walidain. Semua itu menunjukkan bahwa Islam bukan mengganti budaya, tetapi menyambung benang-benang kebaikan yang sudah ada.
Para ulama dahulu memahami bahwa jiwa manusia tidak pernah hidup dalam ruang kosong. Mereka tumbuh dalam bahasa, simbol, dan cerita leluhur. Membasmi semua itu hanya akan membuat manusia kehilangan identitas, sementara dakwah tidak boleh mencabut manusia dari akar kemanusiaannya. Inilah sebabnya ajaran Islam lebih memilih meluruskan arah budaya ketimbang menggusurnya. Ketika suatu adat sudah mengandung nilai-nilai keadilan, kebijaksanaan, atau etika sosial, Islam cukup memberikan bingkai baru agar nilai itu semakin kuat.
Di Tanah Bugis, Jawa, Sunda, Bali, hingga wilayah timur, kita melihat bagaimana Islam tidak menghapus bahasa daerah. Islam justru masuk melalui syair, pepatah, lontara, atau tembang. Bahasa-bahasa lokal tetap hidup, hanya saja mendapatkan nafas rohani baru. Adat tidak dimusnahkan, tetapi dibimbing agar manusia berada pada nilai kebenaran yang lebih sejati. Menjaga adat yang selaras dengan syariat dianggap sebagai bagian dari menjaga martabat manusia.
Jika ditelusuri, para wali dan ulama penyebar Islam lebih memilih melakukan transformasi daripada konfrontasi. Mereka melihat budaya sebagai wadah, sementara isi wadah itu yang perlu dibenahi. Upacara-upacara simbolik yang tidak bertentangan dengan tauhid dipertahankan, sementara unsur yang tidak sesuai diarahkan secara perlahan. Itulah yang membuat masyarakat lokal merasa bahwa Islam bukan ancaman bagi identitas mereka, melainkan berkah yang menjernihkan pemahaman hidup.
Banyak tradisi leluhur ternyata sudah memiliki nilai kesucian, penghormatan, dan ketertiban sosial. Islam datang sebagai penjelas, bukan penghancur. Ajaran akhlak dalam Islam sesungguhnya menemukan lahan subur dalam budaya Nusantara yang menghargai sopan santun dan budi pekerti. Maka perjumpaan keduanya menjadi perjumpaan yang saling menguatkan, bukan saling menyingkirkan.
Jika Islam datang dengan semangat menghapus budaya, tentu masyarakat akan menolak dan mempertahankan warisan leluhurnya. Tapi sejarah berkata lain. Islam diterima dengan tangan terbuka karena ia menghormati manusia beserta identitas budayanya. Ia tidak memaksa masyarakat melepas pakaian adatnya, tetapi mengajarkan nilai moral yang memperindah pakaian itu dengan cahaya tauhid.
Sejak awal, Nabi Muhammad mengajarkan bahwa setiap masyarakat memiliki hikmah. Bahkan dalam masyarakat Arab pra-Islam, ada nilai-nilai terpuji seperti kejujuran, kemurahan hati, dan kesetiaan yang tetap dipertahankan setelah turunnya wahyu. Prinsip ini menjadi pedoman bagi ulama dalam berdialog dengan budaya lokal. Mereka memegang kaidah bahwa yang baik mesti dipertahankan, yang keliru diperbaiki, dan yang bertentangan dengan tauhid ditinggalkan.
Kehadiran Islam yang lembut terhadap budaya membuat agama ini mampu bertumbuh hingga ke pedalaman. Orang-orang tidak merasa dipaksa “menjadi orang lain” untuk masuk Islam. Mereka tetap menjadi anak dari leluhurnya, hanya saja kini membawa ajaran yang menuntun langkah dengan nilai-nilai ilahiah. Dalam proses itu, budaya tidak mati, melainkan menemukan arah baru yang lebih bermakna.
Tradisi ziarah, selamatan, penghormatan kepada orang tua, atau nilai kesetiaan pada tanah kelahiran adalah contoh bagaimana warisan leluhur bersenyawa dengan etika Islam. Masyarakat tidak merasa terbagi antara identitas adat dan identitas keagamaan. Keduanya justru menyatu dalam keseharian, menjadi kekuatan sosial yang memperkukuh hubungan antarmanusia.
Di banyak tempat, masjid-masjid kuno dibangun dengan arsitektur lokal. Ini menandakan bahwa Islam tidak memaksa bentuk tunggal tentang ekspresi budaya. Rumah Allah tetap rumah Allah, tetapi sentuhan lokal membuatnya terasa dekat dan akrab bagi masyarakat. Arsitektur itu menjadi bukti bahwa budaya tidak hilang ketika Islam hadir. Ia justru memperindah ruang spiritual yang baru tumbuh.
Kita bisa melihat bagaimana Islam lebih memilih berakulturasi. Ia tidak menghapus tari tradisional, melainkan memberi batasan moral agar tetap menjaga martabat. Ia tidak menolak seni lokal, tetapi membimbingnya supaya menyampaikan pesan etis dan kemanusiaan. Semua itu menunjukkan bahwa budaya tidak dianggap sebagai musuh, tetapi sebagai kekayaan ruang dakwah.
Perjumpaan Islam dan budaya leluhur sesungguhnya adalah pertemuan dua arus kebijaksanaan. Budaya membawa pengalaman panjang manusia, sementara Islam membawa bimbingan suci yang menyempurnakan perjalanan itu. Ketika keduanya bertemu, lahirlah bentuk peradaban yang lembut, adaptif, dan manusiawi. Ini pula yang membuat identitas keislaman di Nusantara terasa khas dan membumi.
Pada akhirnya, Islam tidak datang untuk menumpahkan cat putih pada kanvas budaya leluhur. Ia datang sebagai pelukis yang menambah warna, memperjelas garis, dan memperindah makna lukisan yang sudah ada. Budaya leluhur tetap menjadi dasar, sementara Islam menjadi cahaya yang menuntun manusia menuju kehidupan yang lebih bermartabat.
Perpaduan ini memperlihatkan bahwa keindahan Islam justru tampak ketika ia menyatu dengan kearifan lokal. Di sanalah agama ini hidup, tumbuh, dan mengakar, bukan sebagai kekuatan yang menghapus, tetapi sebagai rahmat yang meneguhkan jati diri manusia.
Oleh: Zaenuddin Endy
Founder Komunitas Pecinta Indonesia dan Ulama) (KOPINU)