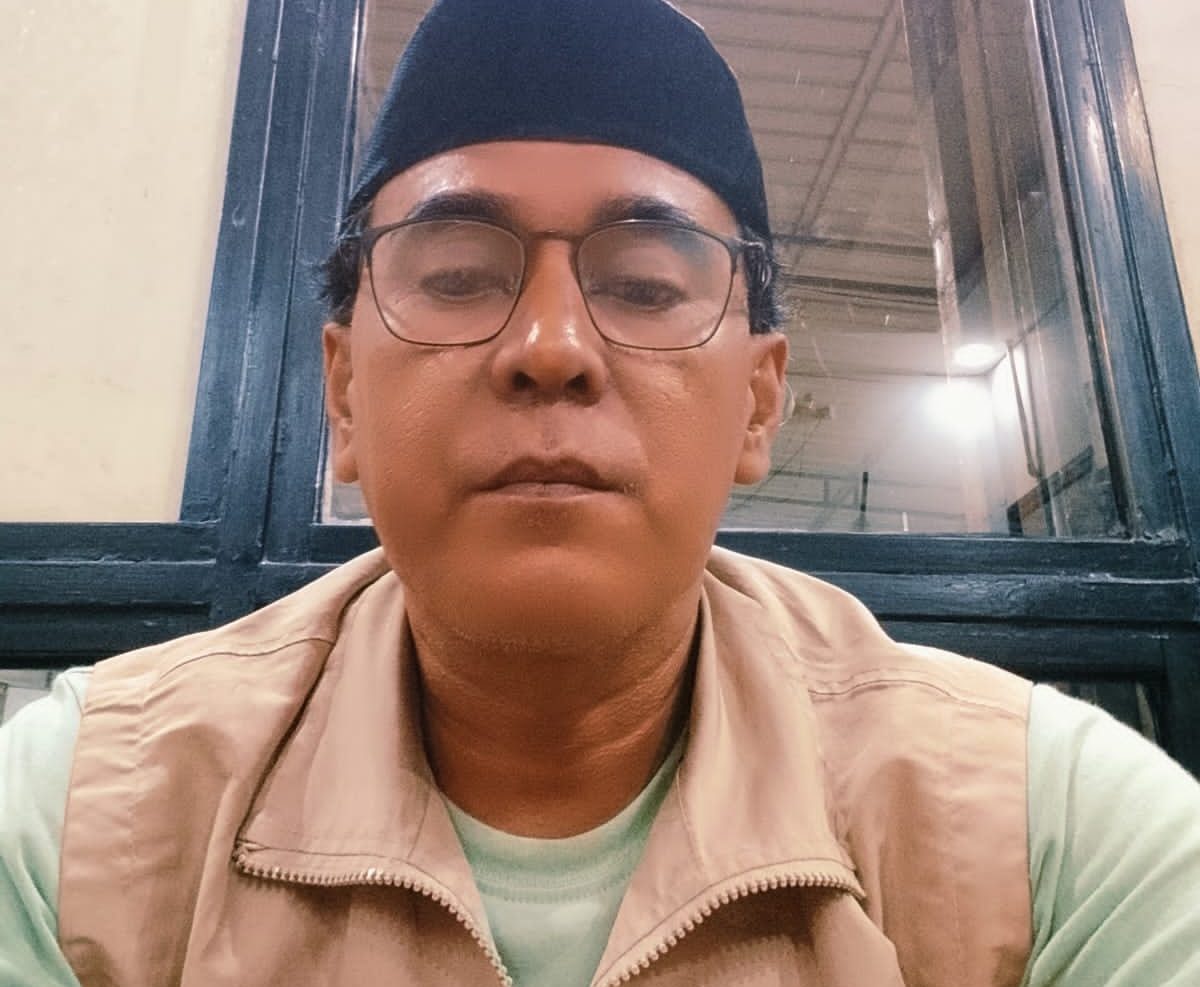Tawassul adalah salah satu ajaran luhur dalam Islam yang sering menjadi jembatan spiritual antara hamba dan Tuhannya. Secara etimologis, tawassul berasal dari kata wasîlah yang berarti perantara atau sarana mendekatkan diri kepada sesuatu. Dalam konteks keagamaan, tawassul berarti mencari kedekatan kepada Allah dengan cara memohon melalui perantara amal saleh, doa orang saleh, atau keberkahan para nabi dan wali. Praktik ini memiliki dasar kuat dalam Al-Qur’an dan sunnah, serta telah menjadi bagian integral dari khazanah spiritual umat Islam sepanjang sejarah.
Al-Qur’an menegaskan pentingnya wasîlah dalam firman-Nya: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah untuk mendekat kepada-Nya” (QS. Al-Ma’idah: 35). Ayat ini mengandung makna bahwa manusia tidak dapat mendekat kepada Allah semata-mata dengan keinginan pribadi, tetapi melalui jalan yang telah Dia ridai. Para mufasir klasik seperti Imam Al-Qurtubi dan Ibn Katsir menjelaskan bahwa wasîlah mencakup segala bentuk ketaatan, amal saleh, dan doa yang dapat membawa seseorang kepada keridhaan Allah.
Tawassul menjadi penting karena ia mengajarkan manusia untuk tidak sombong di hadapan Tuhan. Seorang hamba yang bertawassul menyadari keterbatasannya; ia tahu bahwa dirinya penuh dosa dan kelemahan, sehingga membutuhkan perantara yang memiliki kedekatan dengan Allah. Ini bukan bentuk pengkultusan, melainkan pengakuan spiritual bahwa ada makhluk yang lebih mulia yang dapat menjadi sebab terkabulnya doa. Kerendahan hati semacam ini justru menumbuhkan ketawadhuan, yang merupakan inti dari ibadah sejati.
Rasulullah Saw sendiri mengajarkan tawassul dalam banyak kesempatan. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, sahabat buta datang kepada Rasulullah Saw meminta doa agar sembuh. Rasulullah mengajarkannya doa yang berisi permohonan kepada Allah dengan menyebut nama beliau: “Ya Allah, aku memohon kepada-Mu dan bertawassul kepada-Mu dengan Nabi-Mu Muhammad, Nabi rahmat.” Hadis ini menjadi dasar utama bahwa tawassul dengan perantara Nabi adalah amalan yang sah dan diajarkan langsung oleh beliau sendiri.
Selain dengan Nabi, para sahabat juga bertawassul dengan amal saleh mereka. Kisah terkenal tentang tiga orang yang terjebak di dalam gua menjadi bukti nyata. Masing-masing memohon kepada Allah dengan menyebut amal terbaik yang pernah dilakukan, dan setiap kali mereka bertawassul, batu yang menutup gua bergeser sedikit demi sedikit hingga mereka dapat keluar. Peristiwa ini menunjukkan bahwa tawassul dengan amal saleh sendiri adalah bentuk pengakuan terhadap nilai amal dan rahmat Allah yang luas.
Dalam tradisi Ahlussunnah wal Jama’ah, tawassul juga dilakukan melalui para wali dan ulama yang saleh. Para ulama besar seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Nawawi, dan Imam Subki mengakui kebolehan bertawassul dengan para kekasih Allah, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Mereka memahami bahwa tawassul bukanlah penyembahan kepada selain Allah, melainkan permohonan kepada Allah dengan menyebut nama hamba-hamba-Nya yang dicintai. Semua kekuatan tetap bersumber dari Allah semata.
Tawassul memiliki nilai teologis yang mendalam. Ia menegaskan konsep wasathiyah (moderasi) dalam beragama bahwa manusia tidak bisa langsung menuntut kepada Tuhan seolah-olah setara, namun juga tidak boleh menganggap perantara sebagai tandingan bagi Tuhan. Dalam keseimbangan inilah letak keindahan tawassul: ia menjaga adab hamba di hadapan Rabb-nya, sekaligus mengajarkan cinta kepada para kekasih Allah yang menjadi cermin keteladanan.
Lebih jauh, tawassul memperkaya kehidupan spiritual dengan menghadirkan rasa kedekatan dan kasih sayang. Ketika seseorang bertawassul melalui Nabi atau wali, sesungguhnya ia sedang menumbuhkan rasa cinta dan penghormatan kepada mereka. Cinta inilah yang menjadi bahan bakar keimanan, sebagaimana sabda Nabi Saw, “Tidak sempurna iman seseorang hingga ia mencintaiku lebih dari dirinya sendiri.” Tawassul dengan Nabi berarti meneguhkan ikatan batin dengan suri teladan terbaik umat manusia.
Dari sisi psikologis, tawassul menumbuhkan harapan dan ketenangan. Dalam keadaan terdesak, manusia cenderung membutuhkan pegangan yang konkret. Dengan bertawassul melalui sosok mulia atau amal saleh, hati menjadi lebih mantap dan doa lebih khusyuk. Rasa percaya diri spiritual meningkat karena ia merasa dekat dengan sumber rahmat. Tawassul menjadi terapi rohani yang menenangkan jiwa dan menumbuhkan optimisme dalam menghadapi ujian hidup.
Dalam tradisi Islam Nusantara, tawassul telah menjadi bagian dari ritual kolektif yang sarat makna. Umat Islam di pesantren, majelis zikir, dan tarekat membaca doa tawassul sebagai pembuka dalam setiap majelis. Mereka menyebut nama para Nabi, sahabat, dan ulama sebagai bentuk penghormatan sekaligus sarana mengundang keberkahan. Tradisi ini menumbuhkan kesadaran spiritual bahwa agama bukan sekadar hubungan vertikal, tetapi juga horizontal dengan para pewaris ilmu dan rahmat.
Sayangnya, sebagian kalangan memandang tawassul sebagai bid‘ah atau perbuatan syirik. Pandangan ini muncul karena kesalahpahaman terhadap hakikat tawassul. Mereka mengira bahwa tawassul berarti meminta kepada selain Allah, padahal para ulama telah menegaskan bahwa hakikat doa tetap ditujukan kepada Allah semata. Perantara hanyalah bentuk adab, bukan objek penyembahan. Seperti halnya seseorang meminta doa kepada orang saleh yang masih hidup, tawassul kepada mereka yang telah wafat pun memiliki esensi yang sama: memohon kepada Allah melalui hamba-Nya yang dicintai.
Tawassul juga memiliki nilai sosial yang besar. Ia mempererat ikatan umat dengan ulama dan para wali, menjaga tradisi penghormatan kepada orang-orang saleh. Dalam masyarakat modern yang mulai kehilangan keteladanan moral, tawassul mengingatkan kita akan pentingnya sanad spiritual, rantai keilmuan dan keikhlasan yang menghubungkan generasi demi generasi menuju Rasulullah Saw. Melalui tawassul, warisan spiritual Islam tetap hidup dan terpelihara.
Bagi para sufi, tawassul adalah jantung dari perjalanan ruhani. Mereka memahami bahwa untuk sampai kepada Allah, diperlukan bimbingan ruhani dari guru yang telah menempuh jalan ma‘rifat. Tawassul kepada guru bukan berarti menggantikan posisi Tuhan, melainkan mengikuti jejak mereka dalam mendekat kepada-Nya. Dalam pandangan sufistik, tawassul adalah cinta yang berjenjang, cinta kepada kekasih Allah yang mengantarkan kepada cinta kepada Allah itu sendiri.
Dalam konteks etika spiritual, tawassul mengajarkan pentingnya menghargai perantara kebaikan. Sebagaimana air mengalir melalui sungai untuk mencapai laut, rahmat Allah pun sering sampai kepada hamba melalui perantara doa dan amal orang-orang mulia. Kesadaran ini melahirkan rasa syukur dan penghargaan kepada sesama manusia sebagai bagian dari sistem kasih sayang Ilahi.
Tawassul bukan hanya praktik ritual, tetapi juga simbol kesalingan antara yang mencintai dan yang dicintai di jalan Tuhan. Ia menunjukkan bahwa dalam Islam, hubungan antar-manusia memiliki dimensi transendental. Dengan bertawassul, seorang hamba tidak berjalan sendiri; ia membawa doa para kekasih Allah yang menjadi penopang spiritual dalam menuju cahaya.
Tawassul adalah pengingat bahwa rahmat Allah begitu luas dan dapat dijangkau melalui banyak jalan yang sah dalam syariat. Ia menumbuhkan rasa cinta, kerendahan hati, dan penghargaan kepada para pewaris cahaya kenabian. Siapa yang memahami hakikat tawassul dengan benar akan menemukan kelembutan dalam beragama, tidak kaku, tidak fanatik, tetapi penuh cinta dan adab. Sebab, tawassul bukan hanya jalan menuju terkabulnya doa, tetapi juga jalan menuju kedekatan hati dengan Allah yang Maha Rahman.
Oleh: Zaenuddin Endy
Kordinator Lajnah Ta’lif wa an-Nasyr JATMAN Sulawesi Selatan