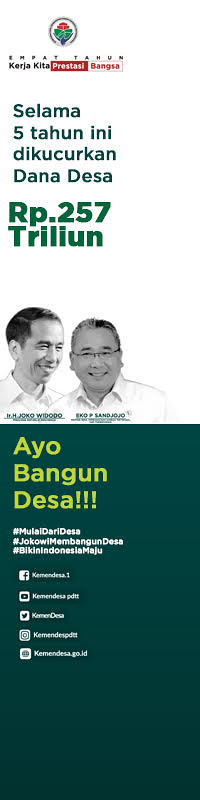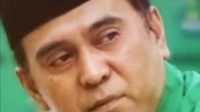Tarekat di Sulawesi Selatan menempati posisi penting dalam sejarah Islamisasi dan perkembangan tradisi keagamaan masyarakat Bugis-Makassar. Kehadirannya tidak hanya dimaknai sebagai jalan spiritual menuju kedekatan dengan Allah, melainkan juga sebagai institusi sosial yang membentuk pola interaksi, solidaritas, dan bahkan perlawanan terhadap kekuasaan kolonial. Jejak panjang tarekat menunjukkan bahwa Islam di Sulawesi Selatan tumbuh bukan semata-mata melalui syariat lahiriah, melainkan juga melalui dimensi batiniah yang sarat dengan nilai tasawuf.
Dalam konteks sejarah, sejumlah tarekat besar pernah hadir dan berpengaruh di Sulawesi Selatan, antara lain Khalwatiyah, Qadiriyah, Sammaniyah, dan Syattariyah. Khalwatiyah dikenal luas sejak abad ke-17 dan menjadi salah satu tarekat paling berpengaruh, khususnya di kalangan kerajaan-kerajaan Bugis dan Makassar. Peran para mursyid dan ulama lokal membuat tarekat ini mampu beradaptasi dengan tradisi budaya setempat tanpa kehilangan akar sufistiknya. Kehadiran tarekat ini juga turut mewarnai corak keberislaman masyarakat yang cenderung menekankan keseimbangan antara lahir dan batin.
Tarekat Sammaniyah yang dibawa oleh ulama keturunan Arab juga menorehkan pengaruh mendalam, terutama dalam tradisi zikir kolektif yang dikenal luas di kalangan pesantren dan komunitas tarekat. Tradisi zikir berjamaah tidak hanya menjadi sarana spiritual, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan rasa kebersamaan. Dalam praktiknya, tarekat berfungsi ganda: sebagai wahana peningkatan spiritualitas sekaligus sebagai jaringan sosial yang memelihara solidaritas komunitas.
Pada masa kolonial, tarekat di Sulawesi Selatan sering terlibat dalam perlawanan terhadap Belanda. Sejumlah mursyid tidak hanya berfungsi sebagai pembimbing ruhani, tetapi juga menjadi tokoh perlawanan. Hal ini memperlihatkan bahwa tarekat memiliki peran ganda: memperkuat iman umat sekaligus menjadi basis perjuangan politik. Fenomena ini menunjukkan keterkaitan erat antara agama, budaya, dan politik di kawasan Bugis-Makassar.
Selain dimensi politik, tarekat juga memengaruhi kehidupan budaya masyarakat. Tradisi maulid, zikir, dan barzanji di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan banyak dipengaruhi oleh amalan-amalan tarekat. Melalui ritual-ritual tersebut, masyarakat menemukan ruang ekspresi religius yang juga sarat makna budaya. Dengan demikian, tarekat tidak hanya bergerak di ruang privat individu, tetapi juga di ruang publik yang menyatukan masyarakat dalam pengalaman religius bersama.
Jejak tarekat di Sulawesi Selatan juga dapat ditelusuri melalui karya-karya ulama lokal yang menulis kitab-kitab tasawuf. Beberapa di antaranya mengadaptasi ajaran tarekat yang mereka pelajari dari Timur Tengah atau Jawa, lalu mengajarkannya dengan bahasa dan istilah lokal. Fenomena ini menunjukkan proses kreatif dalam transmisi ilmu tasawuf yang tidak kaku, melainkan lentur terhadap konteks lokal.
Kedudukan mursyid sebagai figur sentral dalam tarekat memberi warna tersendiri dalam struktur sosial masyarakat Sulawesi Selatan. Mursyid tidak hanya dihormati karena otoritas keilmuannya, tetapi juga karena dianggap memiliki karamah dan kedekatan dengan Tuhan. Status ini membuat mursyid berfungsi sebagai patron spiritual yang mengikat murid-muridnya dalam jejaring yang solid. Dalam konteks Bugis-Makassar, relasi ini seringkali paralel dengan pola patron-klien dalam budaya lokal.
Meskipun demikian, tarekat di Sulawesi Selatan tidak terlepas dari kritik. Sebagian kalangan menilai bahwa praktik tarekat seringkali cenderung formalistik dan simbolistik, terlalu menekankan pada ritual lahiriah seperti zikir berjamaah atau bai‘at, sementara esensi spiritual kadang terabaikan. Kritik ini mencerminkan adanya ketegangan antara upaya menjaga tradisi dan kebutuhan untuk merelevansikan ajaran tarekat dengan tantangan modernitas.
Dalam perkembangan kontemporer, tarekat tetap memiliki daya tarik, khususnya di tengah arus globalisasi yang membawa keresahan spiritual. Banyak masyarakat kembali mencari ketenangan melalui tarekat sebagai alternatif dari kehidupan modern yang materialistik. Di pesantren-pesantren Sulawesi Selatan, tarekat juga tetap diajarkan sebagai bagian dari kurikulum tasawuf, meskipun dalam bentuk yang lebih terstruktur dan ilmiah.
Eksistensi tarekat juga menjadi sarana penting dalam menjaga moderasi beragama. Ajaran-ajaran tarekat yang menekankan cinta, kasih sayang, dan kedekatan dengan Tuhan menjadi benteng terhadap radikalisme. Melalui penghayatan sufistik, tarekat menumbuhkan sikap tasamuh (toleransi), tawassuth (moderat), dan tawazun (seimbang). Nilai-nilai ini sejalan dengan tradisi Islam Nusantara yang mengedepankan harmoni sosial.
Selain itu, tarekat berperan dalam membangun identitas religius masyarakat Bugis-Makassar. Identitas ini tidak hanya berbasis pada syariat formal, melainkan juga pada spiritualitas yang mendalam. Penghayatan terhadap tarekat menjadikan masyarakat lebih terbuka terhadap pluralitas, sekaligus lebih teguh memelihara tradisi keislaman lokal. Dengan demikian, tarekat bukan hanya fenomena keagamaan, tetapi juga bagian integral dari konstruksi identitas budaya.
Peran tarekat dalam bidang pendidikan juga signifikan. Banyak pesantren dan madrasah di Sulawesi Selatan yang menjadi pusat penyebaran tarekat. Santri tidak hanya belajar ilmu-ilmu syariat, tetapi juga dibekali dengan latihan ruhani melalui zikir, wirid, dan suluk. Hal ini menciptakan keseimbangan antara intelektualitas dan spiritualitas, antara akal dan hati.
Namun, tarekat menghadapi tantangan besar di era modern. Arus rasionalisme, sekularisme, dan liberalisasi agama seringkali membuat tarekat dianggap tidak relevan. Sebagian generasi muda menganggap tarekat sebagai praktik kuno yang tidak sesuai dengan zaman. Di sisi lain, ada pula kecenderungan komersialisasi tarekat, di mana praktik spiritual berubah menjadi sekadar simbol status sosial. Tantangan-tantangan ini menuntut tarekat untuk melakukan revitalisasi.
Revitalisasi tarekat dapat dilakukan melalui reinterpretasi ajaran-ajaran sufistik agar sesuai dengan kebutuhan zaman. Misalnya, menekankan aspek etika, spiritualitas universal, dan pengembangan karakter dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara ini, tarekat dapat tetap relevan tanpa kehilangan otentisitasnya. Peran para mursyid kontemporer menjadi penting untuk mengarahkan tarekat agar tetap menjadi sumber pencerahan dan bukan sekadar rutinitas.
Pada akhirnya, jejak tarekat di Sulawesi Selatan membuktikan bahwa spiritualitas tidak pernah terpisah dari budaya dan sejarah. Tarekat hadir sebagai ruang perjumpaan antara dimensi ilahi dengan realitas sosial. Ia menjadi wadah di mana nilai-nilai keagamaan bertemu dengan kearifan lokal, menghasilkan sintesis yang khas Bugis-Makassar. Dari sinilah kita dapat memahami bahwa Islam di Sulawesi Selatan bukan hanya tentang syariat, tetapi juga tentang hakikat yang berakar dalam tarekat.
Dengan demikian, kajian tentang tarekat di Sulawesi Selatan tidak hanya penting bagi pemahaman sejarah Islam lokal, tetapi juga bagi pengembangan wacana Islam Nusantara secara lebih luas. Jejak tarekat merupakan saksi bagaimana masyarakat Bugis-Makassar mengolah tradisi sufistik menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, menghubungkan masa lalu dengan masa kini, serta mempersiapkan masa depan spiritualitas Islam yang lebih inklusif dan humanis.
Daftar Pustaka
Abdullah, Irwan. Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
Azra, Azyumardi. Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII. Jakarta: Kencana, 2013.
Bruinessen, Martin van. Tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia. Bandung: Mizan, 1992.
Nasution, Harun. Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya. Jakarta: UI Press, 1985.
Syam, Nur. Islam Pesisir. Yogyakarta: LKiS, 2005.
Zuhri, Saifuddin. Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia. Bandung: Al-Ma’arif, 1981.
Pelras, Christian. The Bugis. Oxford: Blackwell, 1996.
Poelinggomang, Edward L. Sejarah Islam di Sulawesi Selatan. Makassar: Balai Litbang Agama Makassar, 2011.
Oleh: Zaenuddin Endy
Koordinator LTN Imdadiyah JATMAN Sulawesi Selatan