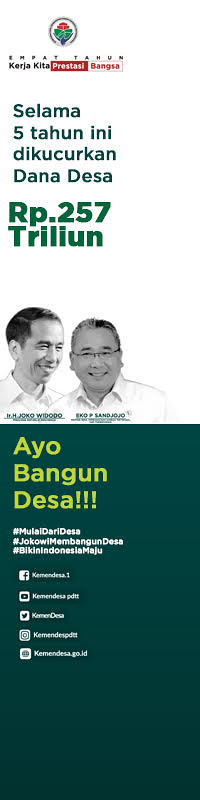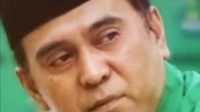Tarekat Qadiriyah merupakan salah satu jaringan tasawuf tertua dalam sejarah Islam yang memiliki pengaruh luas hingga ke kawasan Nusantara, termasuk di Sulawesi Selatan. Di antara daerah yang menjadi pusat persebarannya adalah Kabupaten Sinjai, sebuah wilayah di jazirah selatan Pulau Sulawesi yang dikenal sebagai daerah persinggahan ulama dan pedagang dari berbagai pusat keislaman. Dari sekian tokoh yang berperan dalam proses Islamisasi melalui jalur tarekat, nama Syekh Ahmad muncul sebagai salah satu penggerak awal yang memperkenalkan ajaran Qadiriyah di daerah ini, terutama pada abad ke-17. Ia disebut dalam beberapa sumber lokal sebagai figur ulama mursyid yang mengajarkan amalan zikir, wirid, dan suluk berdasarkan sanad tarekat yang sampai kepada Syekh Abdul Qadir al-Jailani di Baghdad.
Dalam konteks sejarah lokal, penyebaran Islam di Sinjai tidak bisa dilepaskan dari peran jaringan ulama Bugis-Makassar yang berhubungan dengan pusat-pusat tarekat di Aceh dan Jawa. Menurut Muh. Anis (2014), Islamisasi di Sinjai bersifat top-down, di mana para bangsawan dan elite kerajaan menerima ajaran Islam melalui ulama sufi yang telah mendapatkan ijazah tarekat di luar daerahnya. Salah satu nama yang tercatat dalam silsilah keilmuan tersebut adalah Syekh Ahmad bin Abdullah al-Bugisi, seorang ulama yang diyakini belajar tasawuf di luar Sulawesi, kemudian kembali ke tanah Bugis untuk membimbing masyarakat. Melalui perantaraannya, tarekat Qadiriyah menjadi sarana pembinaan spiritual sekaligus penguatan identitas keislaman masyarakat Sinjai.
Tarekat Qadiriyah sendiri menekankan ajaran tentang tauhid, ikhlas, dan pembentukan akhlak batin melalui amalan dzikir “lā ilāha illallāh” secara berulang-ulang. Dalam ajaran Syekh Ahmad kepada para santrinya, dzikir tidak semata aktivitas ritual, melainkan media penyucian hati (tazkiyah al-nafs) yang menjadi jalan menuju ma’rifat kepada Allah. Pengajaran ini mendapat sambutan luas karena sejalan dengan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Bugis yang menjunjung tinggi konsep siri’ na pacce, yakni kehormatan diri dan solidaritas sosial. Dengan demikian, tarekat Qadiriyah di Sinjai bukan hanya sistem spiritual, melainkan juga menjadi fondasi moral masyarakat.
Lokasi penyebaran utama tarekat Qadiriyah di Sinjai tercatat di daerah Baringeng (Sinjai Timur) dan Tafillasa’ (Sinjai Tengah). Dua kawasan ini menjadi pusat suluk dan majelis zikir yang dipimpin oleh Syekh Ahmad dan murid-muridnya. Kehadiran tarekat di sana memperlihatkan transformasi religius masyarakat dari sistem kepercayaan lokal menuju Islam yang bercorak sufistik. Dalam beberapa manuskrip dan cerita lisan yang masih hidup di kalangan masyarakat setempat, nama Syekh Ahmad sering disebut bersamaan dengan dua tokoh lain: Syekh Abdul Rahman dan Syekh Abdul Jalil, keduanya juga dikenal sebagai pembimbing spiritual tarekat Qadiriyah. Mereka membentuk jaringan pengajaran yang terus berlanjut hingga abad ke-18.
Dalam perjalanan sejarahnya, tarekat Qadiriyah di Sinjai mengalami proses adaptasi yang dinamis terhadap struktur sosial dan adat setempat. Masyarakat Bugis dikenal memiliki sistem sosial yang kuat dengan nilai hierarkis dan penghormatan terhadap tokoh agama. Syekh Ahmad memanfaatkan struktur ini dengan membangun hubungan guru-murid (murshid–murid) yang didasarkan pada penghormatan dan ketaatan spiritual. Dalam praktiknya, majelis dzikir Qadiriyah di Sinjai tidak hanya berfungsi sebagai forum keagamaan, tetapi juga sebagai ruang solidaritas sosial, tempat masyarakat saling menolong dan berbagi pengetahuan agama.
Salah satu keunikan ajaran Syekh Ahmad adalah kemampuannya menggabungkan antara ajaran Qadiriyah yang bersumber dari Baghdad dengan nilai-nilai Bugis yang sarat etika lokal. Misalnya, dalam setiap pengajian, ia menekankan pentingnya kejujuran (lempu’), kesabaran (sabar), dan rasa malu (siri’) sebagai syarat penyucian diri. Nilai-nilai ini menunjukkan adanya sinkretisasi moral antara tasawuf Islam dan kebijaksanaan lokal Bugis. Karena itu, tarekat Qadiriyah versi Sinjai dapat dianggap sebagai bentuk Islam lokal yang khas—sebuah model akulturasi spiritual yang harmonis antara Islam dan budaya.
Menurut penelitian yang dilakukan di Repositori UIN Alauddin Makassar (Anis, 2014), Qadiriyah, bersama tarekat Khalwatiyah dan Sattariyah, menjadi tiga sistem spiritual utama yang berkembang di Sinjai. Ketiganya berinteraksi secara damai dan sering kali berbagi ruang dakwah. Dalam majelis yang dipimpin oleh Syekh Ahmad, kadang hadir pula penganut tarekat lain untuk mendengarkan pengajian atau mengikuti dzikir bersama. Hal ini memperlihatkan bahwa Syekh Ahmad mengajarkan tasawuf yang inklusif, tanpa menonjolkan eksklusivitas tarekat. Prinsip ini kelak menjadi karakter umum tarekat-tarekat di Sulawesi Selatan.
Selain berfungsi spiritual, tarekat Qadiriyah juga berperan penting dalam pendidikan dan pembinaan masyarakat. Syekh Ahmad dikenal mendirikan pondok pengajian sederhana yang menjadi tempat belajar fikih, tauhid, dan tasawuf. Sistem pendidikan ini kemudian melahirkan generasi ulama lokal yang melanjutkan dakwahnya ke berbagai wilayah, termasuk Bone, Bulukumba, dan Gowa. Dalam konteks ini, tarekat berfungsi sebagai institusi pendidikan nonformal yang membentuk karakter santri dan memperkuat jaringan keulamaan Bugis-Makassar.
Jejak tarekat Qadiriyah di Sinjai juga terlihat dalam bentuk ritual tahunan seperti maulid, ratib Qadiriyah, dan mappanre temme (selamatan khatam dzikir). Upacara-upacara ini menggabungkan nilai-nilai spiritual Islam dengan budaya lokal. Para jamaah Qadiriyah biasanya melakukan pembacaan manaqib Syekh Abdul Qadir al-Jailani, disertai doa bersama dan kenduri, yang dimaknai sebagai ekspresi syukur dan penguatan ukhuwah. Tradisi ini bertahan hingga kini di beberapa desa di Sinjai, meskipun mengalami modifikasi seiring dengan perubahan sosial dan modernisasi.
Dalam pandangan antropologis, tarekat Qadiriyah di Sinjai bukan hanya lembaga keagamaan, melainkan juga pusat produksi makna bagi masyarakat Bugis. Melalui zikir dan pengajian, masyarakat menemukan bentuk ekspresi spiritual yang tidak bertentangan dengan adat. Tarekat menjadi jembatan antara agama dan budaya, antara tasawuf dan etika sosial. Oleh karena itu, warisan Syekh Ahmad memiliki nilai strategis dalam memahami bagaimana Islam menyatu dengan identitas lokal masyarakat Bugis.
Namun, seperti banyak tarekat lain, Qadiriyah di Sinjai menghadapi tantangan modernitas. Arus pendidikan formal, globalisasi dakwah, dan munculnya gerakan puritan menyebabkan sebagian praktik tarekat dianggap tidak relevan atau bahkan bid‘ah. Akan tetapi, penelitian lapangan menunjukkan bahwa tarekat ini tetap bertahan berkat adaptasi sosialnya: pengajaran tasawuf kini dikemas dalam bentuk majelis dzikir harian dan kegiatan sosial-keagamaan seperti santunan dan gotong royong. Generasi penerus Syekh Ahmad menyesuaikan metode dakwah tanpa meninggalkan esensi spiritual yang diwariskan oleh pendiri mereka.
Dalam hal keilmuan, jejak Syekh Ahmad di Sinjai belum banyak terdokumentasi secara tertulis. Kebanyakan informasi berasal dari tradisi lisan dan catatan keluarga ulama. Karena itu, penelitian lebih lanjut terhadap manuskrip Bugis (lontara’) dan naskah-naskah tarekat di pesantren tua Sinjai sangat penting untuk memastikan silsilah keilmuan beliau. Ada indikasi bahwa silsilah ajaran Syekh Ahmad memiliki keterkaitan dengan tarekat Qadiriyah yang berkembang di Aceh dan Jawa, namun belum ditemukan bukti tertulis yang eksplisit. Upaya digitalisasi dan dokumentasi sejarah tarekat lokal menjadi kebutuhan mendesak untuk melestarikan warisan ini.
Kehadiran tarekat Qadiriyah di Sinjai juga turut memperkaya peta keberagamaan Sulawesi Selatan secara keseluruhan. Bila Khalwatiyah lebih menonjol di Gowa dan Maros, serta Sattariyah kuat di Bone dan Wajo, maka Qadiriyah memiliki basis spiritual yang kuat di Sinjai dan Mandar. Hal ini menunjukkan bahwa tiap daerah di Sulawesi Selatan memiliki konfigurasi tarekat yang khas, tetapi semuanya berakar pada orientasi tasawuf Sunni. Sinergi antar tarekat ini berkontribusi terhadap terbentuknya Islam Bugis yang moderat, ramah, dan penuh toleransi.
Secara sosiologis, peran tarekat Qadiriyah di Sinjai melampaui fungsi spiritual semata. Ia berkontribusi pada stabilitas sosial, pengendalian moral masyarakat, serta pelestarian nilai gotong royong. Para pengikut tarekat biasanya terlibat aktif dalam kegiatan sosial-keagamaan dan pembangunan desa. Dalam konteks ini, ajaran Syekh Ahmad terbukti relevan dengan pembangunan karakter masyarakat religius yang beradab.
Hingga kini, beberapa keturunan murid Syekh Ahmad masih menjaga tradisi tarekat Qadiriyah di Sinjai. Mereka memimpin zikir, memberikan bimbingan spiritual, dan menjadi rujukan masyarakat. Di antara mereka ada yang berperan sebagai guru pesantren, imam masjid, atau pembimbing jamaah haji. Ini menunjukkan kontinuitas spiritual yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Warisan Syekh Ahmad tidak berhenti sebagai doktrin, melainkan terus hidup sebagai tradisi rohani dan sosial yang mengakar di hati masyarakat Bugis.
Dengan demikian, jejak Syekh Ahmad dan tarekat Qadiriyah di Sinjai bukan sekadar bagian dari sejarah lokal, tetapi juga bab penting dalam narasi besar Islamisasi Sulawesi Selatan. Tarekat menjadi jembatan antara ajaran universal Islam dan tradisi lokal Bugis, antara spiritualitas dan kebudayaan, antara masa lalu dan masa depan. Syekh Ahmad telah meninggalkan warisan yang tak ternilai—sebuah tradisi sufistik yang meneguhkan moderasi, cinta tanah air, dan nilai kemanusiaan dalam bingkai Islam rahmatan lil ‘alamin.
Daftar Pustaka
Anis, Muh. (2014). Penerimaan Islam di Sinjai Abad XVII: Analisis Perubahan Sosial Keagamaan. Makassar: Repositori UIN Alauddin Makassar.
Alwi, Nurdin (2018). Tarekat di Sulawesi Selatan: Studi Historis dan Sosiologis. Makassar: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama.
Azra, Azyumardi (2004). Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII. Jakarta: Kencana.
Bruinessen, Martin van (1992). Tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia. Bandung: Mizan.
Cawidu, Abdul Gani (1991). Islam dan Budaya Bugis. Ujung Pandang: IAIN Alauddin Press.
Yusuf, Ahmad (2020). Peran Tarekat Qadiriyah dalam Pembinaan Masyarakat di Mandar. Repositori UIN Alauddin Makassar.
Oleh: Zaenuddin Endy
Koordinator LTN Imdadiyah JATMAN Sulawesi Selatan