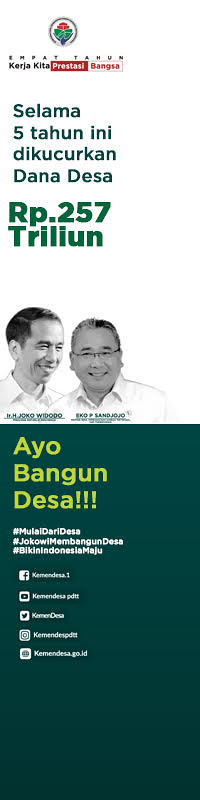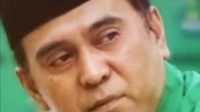Ungkapan Bugis Sobbui Alemu atau “sembunyikan dirimu” merupakan sebuah ekspresi kearifan lokal yang sarat makna spiritual. Di balik kesederhanaan kalimat ini, tersimpan nilai yang sejalan dengan ajaran tasawuf, yakni mengarahkan manusia untuk tidak larut dalam kebanggaan diri dan mencari pengakuan, melainkan menundukkan ego dan menjaga ketulusan hati. Bagi masyarakat Bugis, sikap menyembunyikan diri bukan sekadar perilaku sosial, tetapi sebuah etika hidup yang mengajarkan keseimbangan antara eksistensi pribadi dan kerendahan hati.
Dalam tradisi tasawuf, penyembunyian diri merupakan bagian dari perjalanan spiritual menuju Allah. Para sufi meyakini bahwa amal yang tulus adalah amal yang tidak bergantung pada pengakuan manusia. Dengan menyembunyikan amal kebaikan, seorang hamba menjaga kemurnian niatnya agar tidak terkotori oleh riya atau sum’ah. Di sinilah Sobbui Alemu menemukan relevansinya, sebab ia mendorong setiap insan untuk memfokuskan ibadah semata-mata kepada Allah, bukan kepada pujian sosial.
Imam al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menegaskan bahwa amal yang tersembunyi lebih disukai Allah daripada amal yang diumumkan, kecuali jika ada maslahat yang lebih besar. Prinsip ini sejalan dengan ungkapan Bugis tersebut yang menekankan pentingnya kesederhanaan dan kerahasiaan dalam perbuatan baik. Dengan demikian, Sobbui Alemu dapat dibaca sebagai ajakan untuk mempraktikkan ikhlas, yaitu melakukan segala sesuatu hanya demi keridhaan Ilahi.
Selain menjaga keikhlasan, menyembunyikan diri juga merupakan bentuk latihan spiritual untuk menundukkan hawa nafsu. Dalam tasawuf, nafsu ammarah selalu mendorong manusia untuk mencari kehormatan dan kedudukan. Dengan melatih diri agar tidak haus akan pengakuan, seorang salik sedang berusaha melampaui godaan nafsu. Konsep ini beririsan dengan maqam tawadhu’, yakni kerendahan hati yang lahir dari kesadaran akan keterbatasan diri di hadapan Allah.
Dalam konteks budaya Bugis, Sobbui Alemu bukan berarti menutup diri dari pergaulan atau menolak interaksi sosial. Sebaliknya, ia mengajarkan agar setiap individu menjaga sikap santun, tidak menonjolkan kelebihan diri, serta menghargai orang lain dengan penuh ketulusan. Menyembunyikan diri adalah seni menjaga keseimbangan antara aktualisasi diri dan kerendahan hati, sehingga kehadiran seseorang memberi manfaat tanpa menimbulkan kesombongan.
Keterhubungan nilai Bugis ini dengan tasawuf juga terlihat dari konsep khafa, yaitu kerahasiaan spiritual. Para sufi sering mengingatkan agar seorang murid menjaga hubungan dengan Allah dalam sunyi, jauh dari sorotan manusia. Sebagaimana dikatakan al-Qusyairi, salah satu tanda ikhlas adalah ketika amal saleh tidak berubah meskipun tidak ada seorang pun yang melihat. Nilai ini sangat dekat dengan pesan Sobbui Alemu, yang menuntut seorang insan untuk lebih peduli pada pandangan Allah daripada penilaian manusia.
Selain itu, menyembunyikan diri juga menjadi benteng dari sifat riya yang dapat merusak amal. Dalam perspektif tasawuf, riya merupakan penyakit hati yang halus dan sulit disadari. Dengan melatih diri untuk tidak menonjolkan amal, seorang salik memotong akar riya sebelum ia berkembang. Filosofi Sobbui Alemu dalam hal ini dapat dipahami sebagai etika untuk menjaga kemurnian batin dari kerusakan akibat pencitraan dan pamrih duniawi.
Menariknya, nilai Sobbui Alemu tidak menuntut penghapusan identitas sosial. Justru, ia mengajarkan bahwa kontribusi yang sejati kepada masyarakat lahir dari hati yang bersih. Orang yang tidak mencari pengakuan biasanya bekerja lebih tulus, sebab ia tidak menunggu balasan atau penghargaan. Dalam perspektif ini, menyembunyikan diri melahirkan ketulusan sosial yang menguntungkan orang banyak.
Dalam kerangka sosial, filosofi ini juga dapat memperkuat harmoni. Individu yang tidak menonjolkan diri cenderung lebih dihormati, karena ia menunjukkan sikap rendah hati dan menghargai orang lain. Dalam tradisi Bugis, sikap seperti ini disebut siri’ dalam pengertian positif, yakni menjaga kehormatan dengan tidak merendahkan orang lain melalui kesombongan diri. Dengan demikian, Sobbui Alemu tidak hanya bernilai spiritual, tetapi juga berkontribusi bagi etika sosial.
Dalam kehidupan sehari-hari, praktik menyembunyikan diri bisa diwujudkan dengan berbagai cara sederhana. Misalnya, membantu orang lain tanpa menyebutkan identitas, bersedekah tanpa diketahui, atau menolong tanpa mengharapkan ucapan terima kasih. Semua tindakan ini melatih jiwa untuk lebih fokus pada manfaat yang diberikan ketimbang pada pujian yang diterima.
Relevansi Sobbui Alemu semakin terasa di era modern yang ditandai dengan budaya pamer dan keterbukaan informasi. Media sosial sering mendorong manusia untuk menampilkan setiap amal, bahkan yang bersifat pribadi. Dalam situasi ini, filosofi Bugis yang selaras dengan tasawuf menjadi pengingat agar manusia tidak kehilangan esensi keikhlasan. Menyembunyikan diri menjadi semacam kritik terhadap budaya eksposur yang berlebihan.
Di sisi lain, Sobbui Alemu tidak harus diartikan sebagai larangan mutlak untuk menunjukkan amal. Tasawuf tetap mengakui adanya kondisi ketika menampilkan amal membawa manfaat, seperti memberi teladan atau mengajak orang lain berbuat baik. Namun, yang terpenting adalah kondisi hati: apakah amal itu ditunjukkan untuk Allah atau sekadar mencari pengakuan manusia. Filosofi ini mengajarkan keseimbangan, yakni menjaga niat sekaligus mempertimbangkan maslahat sosial.
Dalam kerangka pendidikan spiritual, ajaran ini dapat menjadi bagian dari strategi membentuk karakter. Pesantren misalnya, dapat menjadikan nilai Sobbui Alemu sebagai etika murid dalam menempuh jalan ilmu. Santri diajarkan untuk belajar dengan tekun tanpa harus selalu menonjolkan pencapaiannya. Dengan cara ini, ilmu tidak hanya menjadi alat meraih kedudukan, tetapi juga jalan menuju kerendahan hati.
Lebih jauh, nilai ini juga relevan dalam membangun moderasi beragama. Seseorang yang terbiasa menyembunyikan diri akan cenderung menghindari sikap ekstrem dalam menampilkan identitas. Ia lebih fokus pada substansi iman dan amal ketimbang pada simbol-simbol lahiriah yang bisa melahirkan klaim kebenaran tunggal. Dengan demikian, Sobbui Alemu membantu terciptanya sikap beragama yang damai, rendah hati, dan penuh penghormatan kepada perbedaan.
Filosofi ini juga dapat dipandang sebagai kontribusi kearifan lokal Bugis terhadap spiritualitas Islam universal. Tasawuf sebagai jalan mendekat kepada Allah sesungguhnya menemukan kekuatannya ketika ia bersenyawa dengan budaya lokal. Sobbui Alemu menjadi bukti bahwa masyarakat Bugis telah menginternalisasi nilai tasawuf dalam kehidupan sehari-hari, sehingga spiritualitas Islam lebih membumi dan kontekstual.
Sobbui Alemu mengajarkan manusia untuk menyadari keterbatasannya, menjaga hati agar tetap ikhlas, dan menghindari jebakan kesombongan. Dalam perspektif tasawuf, menyembunyikan diri adalah jalan menuju maqam fana’, yaitu hilangnya ego di hadapan kebesaran Allah. Nilai ini sekaligus menuntun manusia untuk tetap bermanfaat bagi sesama, tanpa perlu mengumbar jasa. Dengan demikian, Sobbui Alemu bukan hanya pesan budaya Bugis, tetapi juga jalan spiritual yang selaras dengan ajaran Islam.
Daftar Pustaka
Al-Ghazali, Abu Hamid. Ihya’ Ulum al-Din. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2005.
Al-Qusyairi, Abu al-Qasim. Al-Risalah al-Qusyairiyyah fi ‘Ilm al-Tasawwuf. Kairo: Dar al-Ma’arif, 2002.
Arifin, Syamsul. “Tasawuf dan Relevansinya dalam Kehidupan Modern.” Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama, Vol. 24, No. 2 (2023): 155–170.
Basri, Hasan. Kearifan Lokal Bugis dalam Perspektif Islam. Makassar: Pustaka Al-Zikra, 2019.
Mattulada. Latoa: Satu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998.
Nur, Syamsu. “Nilai-Nilai Lokal Bugis sebagai Basis Pendidikan Karakter.” Jurnal Pendidikan Karakter, Vol. 12, No. 1 (2022): 87–102.
Rahim, A. Rasyid. Budaya Bugis dan Nilai-Nilai Religius. Makassar: UIN Alauddin Press, 2020.
Schimmel, Annemarie. Mystical Dimensions of Islam. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1975.
Sya’roni, Ahmad. “Ikhlas dan Riya dalam Perspektif Tasawuf.” Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam, Vol. 11, No. 1 (2022): 45–63.
Syukur, M. Amin. Tasawuf Sosial: Solusi Problem Manusia Modern. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
Oleh: Zaenuddin Endy
Koordinator LTN Imdadiyah JATMAN Sulawesi Selatan