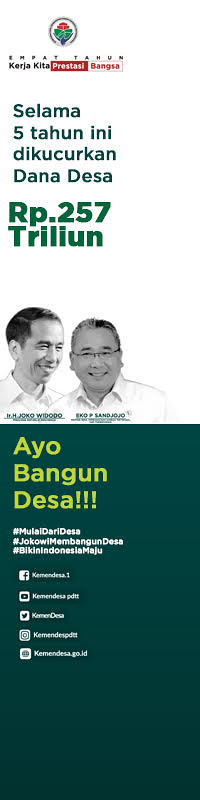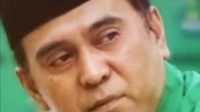Karaeng Binamu Tengnginung Jenne merupakan salah satu figur penting dalam sejarah lokal di wilayah Sulawesi Selatan, khususnya dalam lingkup kerajaan-kerajaan Bugis-Makassar yang pernah berjaya pada abad ke-17 hingga abad ke-19. Nama “Karaeng Binamu” merujuk pada wilayah Binamu yang kini termasuk dalam Kabupaten Jeneponto, sementara “Tengnginung Jenne” merupakan gelar atau panggilan kehormatan yang mencerminkan status sosial-politik serta peran penting yang dimainkan oleh tokoh ini di tengah masyarakatnya.
Dalam struktur tradisional masyarakat Makassar, gelar “Karaeng” menandakan posisi bangsawan atau pemimpin wilayah yang memiliki otoritas atas tanah, rakyat, dan adat. Karaeng Binamu adalah pemegang kekuasaan atas wilayah pesisir selatan Sulawesi yang strategis, baik dari sisi ekonomi maupun politik. Binamu sendiri dikenal sebagai salah satu pusat perdagangan dan pertanian yang subur sejak masa klasik.
Tengnginung Jenne, sebagai tambahan nama, secara harfiah berarti “yang bijak menimbang air” atau secara kiasan bisa dimaknai sebagai pemimpin yang arif dalam menyeimbangkan kekuatan dan kelembutan. Julukan ini menggambarkan karakter kepemimpinan Karaeng Binamu yang dikenal tidak hanya tangguh secara militer, tetapi juga lihai dalam diplomasi, adat, dan penyelesaian konflik.
Pada masa pemerintahan Karaeng Binamu Tengnginung Jenne, wilayah Binamu memainkan peran penting dalam hubungan antara kerajaan Gowa-Tallo dan kerajaan-kerajaan kecil di wilayah selatan seperti Bantaeng, Bulukumba, hingga Tanete dan Bone di timur. Ia dipercaya menjadi perantara dalam menjalin aliansi dan menjaga stabilitas di wilayah perbatasan antara etnis Makassar dan Bugis. Dalam beberapa sumber lisan dan catatan naskah lokal (lontara’), disebutkan bahwa Karaeng Binamu menjadi figur penentu dalam perundingan damai antara penguasa Gowa dan para bangsawan dari Bone setelah masa perang besar Makassar-Bone.
Dalam narasi sejarah lokal, Karaeng Binamu juga dikenang sebagai pelindung adat dan budaya lokal. Ia menjaga keseimbangan antara pengaruh Islam yang semakin kuat dengan sistem sosial-adat tradisional yang sudah mengakar. Karaeng Binamu mendukung dakwah Islam tanpa mengabaikan kearifan lokal, sehingga integrasi nilai-nilai Islam dan budaya Makassar-Bugis terjadi secara damai dan harmonis. Hal ini menjadikannya tokoh yang dihormati baik oleh kalangan ulama maupun masyarakat adat.
Dalam beberapa penuturan masyarakat tua di Binamu dan sekitarnya, Karaeng Binamu dikisahkan sebagai pemimpin yang sering turun langsung ke sawah, menginspeksi irigasi, berbicara langsung dengan petani, serta memantau pasar rakyat. Legenda-legenda tentang kemurahan hatinya, keadilannya dalam mengadili sengketa, serta kepiawaiannya dalam strategi perang masih hidup dalam ingatan kolektif masyarakat Jeneponto hingga kini.
Sayangnya, literatur tertulis yang membahas Karaeng Binamu Tengnginung Jenne secara khusus masih sangat terbatas. Sejumlah informasi hanya dapat diperoleh dari tradisi lisan, lontara yang tersebar di kalangan keluarga bangsawan, serta penggalan cerita rakyat. Oleh karena itu, upaya pelacakan sejarah tokoh ini menjadi penting tidak hanya untuk menegaskan identitas lokal Jeneponto, tetapi juga untuk memperkaya khazanah historiografi Sulawesi Selatan.
Kehadiran Karaeng Binamu dalam percaturan sejarah lokal membuktikan bahwa wilayah seperti Jeneponto tidak pernah menjadi pinggiran dalam sejarah Sulawesi Selatan. Ia justru menjadi simpul penting dalam jaringan kekuasaan, perdagangan, dan penyebaran Islam di pesisir selatan pulau Sulawesi. Dalam konteks ini, Karaeng Binamu Tengnginung Jenne pantas mendapat tempat dalam peta besar sejarah Indonesia, sebagai simbol kearifan lokal, kepemimpinan berbasis nilai, dan ketahanan budaya yang mengakar kuat di tengah perubahan zaman.
Zaenuddin Endy
Komunitas Pecinta Indonesia, Nusantara, dan Ulama (KOPINU)