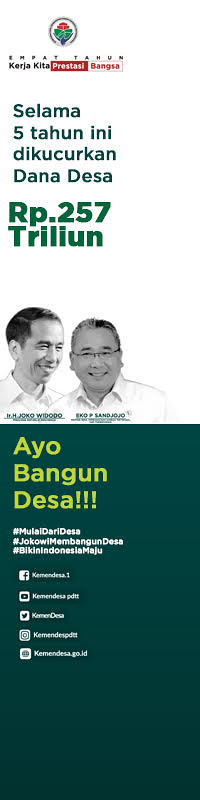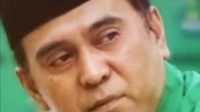Sejarah penyebaran Islam di Tana Toraja merupakan bagian penting dari mozaik Islamisasi Sulawesi Selatan. Di antara tokoh yang tercatat meninggalkan jejak mendalam adalah Guru Siduppa, seorang mubalig yang berasal dari Teteaji, Sidrap. Kehadirannya di Tana Toraja pada paruh akhir abad ke-19 menjadi momentum bersejarah yang menandai lahirnya komunitas Muslim pertama di wilayah yang sebelumnya didominasi oleh kepercayaan lokal Aluk To Dolo dan kemudian misionaris Kristen. Dengan pendekatan damai, kontekstual, dan penuh kearifan, Guru Siduppa berhasil membuka ruang bagi Islam untuk bertumbuh di tanah pegunungan yang dikenal memiliki identitas budaya kuat itu.
Kedatangan Guru Siduppa ke Toraja tidak terjadi secara kebetulan. Ia adalah bagian dari gelombang penyiar Islam dari Sidrap, Enrekang, dan Luwu yang membawa misi dakwah ke daerah pedalaman. Jalur perdagangan, perantauan, dan hubungan kekerabatan menjadi pintu masuk yang alami. Berbeda dengan pendekatan militer yang pernah dicoba pada masa lalu, Guru Siduppa memilih jalur pendidikan dan interaksi sosial. Hal ini membuat pesan-pesan Islam lebih mudah diterima oleh masyarakat Toraja yang pada dasarnya terbuka terhadap ajaran baru selama tidak mengancam tatanan sosial mereka.
Salah satu kisah paling monumental dalam perjalanan dakwah Guru Siduppa adalah pernikahannya dengan Rangga, seorang perempuan bangsawan Toraja. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 1876 dan menandai proses asimilasi Islam pertama yang terakui di Lembang Madandan. Rangga kemudian menjadi Muslimah pertama di wilayah itu, dan rumah tangga yang dibangun bersama Guru Siduppa menjadi simbol keterhubungan antara dua tradisi besar: Islam dari Sidrap dan adat Toraja. Dari sinilah Islam mulai mendapatkan tempat di hati sebagian masyarakat lokal.
Selain melalui pernikahan, Guru Siduppa aktif mendirikan majelis pengajian dan mendidik generasi awal Muslim Toraja. Ia bersama tokoh sezamannya seperti Bora Ele (guru tarekat) dan Uwa’ Ammada (guru tajwid) mengajarkan dasar-dasar Islam, mulai dari membaca Al-Qur’an, tata cara shalat, hingga nilai-nilai akhlak. Dari kelompok kecil ini, terbentuklah komunitas yang semakin solid dan berani menampilkan identitas keislaman mereka. Peran Guru Siduppa tidak hanya sebagai pendakwah, tetapi juga sebagai pendidik dan pengikat komunitas baru yang lahir di tengah dominasi tradisi lokal.
Momentum penting lain dari dakwah Guru Siduppa adalah berdirinya Masjid Jami Madandan sekitar tahun 1858. Masjid ini kelak menjadi pusat syiar Islam di Tana Toraja dan menjadi simbol keberadaan Muslim di kawasan pegunungan tersebut. Dengan adanya masjid, umat Islam di Madandan dapat melaksanakan shalat berjamaah, memperingati hari besar Islam, dan memperkuat solidaritas mereka. Masjid ini juga menjadi ruang interaksi antaragama, sebab masyarakat Toraja yang non-Muslim kerap melihat dan menyaksikan praktik ibadah Islam dengan penuh rasa ingin tahu.
Keberhasilan Guru Siduppa dalam menyebarkan Islam di Toraja erat kaitannya dengan pendekatan dakwah yang ia gunakan. Ia tidak pernah memaksakan ajaran Islam secara frontal, melainkan menyampaikannya dengan bahasa yang membumi dan penuh penghormatan pada adat setempat. Islam diposisikan bukan sebagai agama yang menghapus tradisi, melainkan sebagai ajaran yang memberi makna baru pada nilai-nilai lokal. Misalnya, prinsip menghormati orang tua, menjunjung tinggi persaudaraan, dan menjaga solidaritas sosial ditafsirkan sebagai bagian dari ajaran Islam yang sejalan dengan adat Toraja.
Dalam catatan sejarah, Islamisasi Toraja memang tidak pernah berjalan cepat. Namun, justru karena langkahnya yang lambat dan penuh kearifan, Islam mampu bertahan hingga kini. Guru Siduppa berhasil menanamkan akar keyakinan yang kokoh meski jumlah pemeluknya minoritas. Masyarakat Toraja pada umumnya tetap menghormati umat Islam, dan sebaliknya, umat Islam yang dibimbing oleh Guru Siduppa belajar hidup berdampingan dengan penuh toleransi. Inilah warisan penting dari dakwah yang berlandaskan kasih sayang, bukan penaklukan.
Jejak Guru Siduppa juga dapat dibaca sebagai bagian dari proses akulturasi budaya. Kehadirannya tidak hanya memperkenalkan ritual Islam, tetapi juga memperkaya identitas sosial Toraja dengan nuansa baru. Perkawinan silang, interaksi perdagangan, dan hubungan kekerabatan menciptakan generasi Muslim Toraja yang tetap menghargai akar budaya lokal. Dengan demikian, Islam tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai warna baru dalam keberagaman masyarakat.
Dalam perspektif antropologis, Guru Siduppa dapat diposisikan sebagai agen perubahan yang membawa “inovasi religius” ke dalam masyarakat yang kompleks. Teori difusi inovasi Everett Rogers misalnya, menjelaskan bahwa perubahan sosial dapat diterima jika dilakukan melalui jaringan interpersonal yang terpercaya. Guru Siduppa menggunakan jaringan itu dengan sangat efektif: perkawinan, kekerabatan, dan pendidikan menjadi medium utama dakwah. Hasilnya, Islam diterima bukan karena paksaan, tetapi karena keterhubungan emosional dan sosial.
Penting dicatat bahwa kehadiran Guru Siduppa tidak berdiri sendiri. Ia berjejaring dengan para ulama dan penyiar Islam dari wilayah lain. Hubungan ini memperkaya materi dakwah yang dibawanya dan memberi legitimasi lebih kuat bagi komunitas Muslim di Toraja. Dukungan dari Sidrap dan daerah sekitarnya membuat komunitas Muslim Toraja tidak merasa terisolasi, melainkan bagian dari jaringan besar umat Islam Sulawesi Selatan.
Hingga kini, jejak Guru Siduppa masih dikenang terutama di Lembang Madandan. Masjid Jami Madandan tetap berdiri sebagai saksi bisu perjalanan panjang Islam di Toraja. Setiap kali umat Muslim setempat melaksanakan ibadah, mereka sesungguhnya sedang melanjutkan tradisi yang ditanamkan oleh Guru Siduppa lebih dari seabad lalu. Masjid ini bukan hanya bangunan fisik, tetapi juga simbol eksistensi dan identitas Muslim Toraja yang bertahan dalam dinamika zaman.
Kisah Guru Siduppa mengajarkan bahwa dakwah Islam yang efektif adalah dakwah yang mampu menghormati kearifan lokal. Ia membuktikan bahwa Islam dapat diterima di masyarakat dengan tradisi kuat sekalipun, asalkan disampaikan dengan kelembutan dan kasih sayang. Pendekatan yang penuh kearifan ini sejalan dengan prinsip rahmatan lil ‘alamin, yakni Islam sebagai rahmat bagi semesta alam.
Dalam konteks kekinian, teladan Guru Siduppa sangat relevan. Masyarakat Indonesia yang majemuk membutuhkan pendekatan dakwah yang moderat, dialogis, dan inklusif. Nilai-nilai yang diwariskan oleh Guru Siduppa dapat menjadi inspirasi bagi para penyiar Islam di daerah lain, terutama di wilayah minoritas Muslim. Mengedepankan persaudaraan, menghargai perbedaan, dan mengintegrasikan nilai lokal ke dalam dakwah adalah kunci membangun harmoni sosial.
Jejak Guru Siduppa di Tana Toraja adalah bukti nyata bahwa Islam dapat bertumbuh dalam kondisi apa pun selama dakwah dilakukan dengan hati. Ia adalah pionir yang menorehkan sejarah panjang, meski namanya tidak setenar tokoh-tokoh besar lain di Sulawesi Selatan. Namun, bagi umat Muslim Toraja, Guru Siduppa adalah sosok pelita yang menerangi jalan mereka menuju Islam, dan warisannya akan terus hidup sepanjang zaman.
Oleh: Zaenuddin Endy
Komunitas Pecinta Indonesia, Nusantara, dan Ulama (KOPINU)