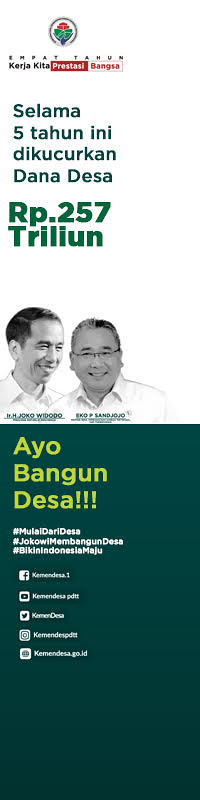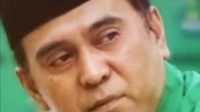Syekh Abdur Razak al-Buni Syams al-Arifin, atau lebih dikenal sebagai Puang MatowaE, merupakan salah satu tokoh ulama besar Bugis pada abad ke-19 yang berperan penting dalam perkembangan Islam, khususnya melalui Tarekat Khalwatiyah Samman. Namanya tercatat dalam sejarah Islam lokal Sulawesi Selatan sebagai seorang mursyid kharismatik yang berhasil menyatukan ajaran tasawuf dengan tradisi budaya Bugis. Kehadirannya menegaskan peran ulama lokal dalam menjaga kesinambungan Islam di Nusantara, sekaligus memperlihatkan betapa kuatnya pengaruh jaringan tarekat dalam proses Islamisasi.
Latar belakang genealogis Syekh Abdur Razak menunjukkan keterkaitan dengan bangsawan Bone. Ia disebut sebagai cucu dari Sultan Ahmad Saleh Syamsuddin yang memerintah Bone pada akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19. Dari garis keluarga ini, terlihat bahwa Syekh Abdur Razak tumbuh dalam lingkungan yang tidak hanya berhubungan dengan kekuasaan politik, tetapi juga keilmuan dan spiritualitas. Namun, berbeda dari kebanyakan bangsawan yang berkutat pada urusan politik, ia lebih memilih jalan keilmuan dan tasawuf.
Dalam tradisi tarekat, nama “al-Buni” yang melekat pada dirinya menunjukkan afiliasi ruhani dengan tradisi sufistik yang panjang, meski sebagian peneliti menafsirkannya sebagai simbol otoritas spiritual semata. Ia dikenal sebagai seorang alim yang memiliki sanad keilmuan kuat, baik dari ulama-ulama lokal maupun dari jaringan ulama internasional yang menghubungkan Sulawesi Selatan dengan Haramain. Jaringan ulama inilah yang memperkuat posisinya sebagai seorang mursyid yang sah dan diterima luas.
Perkembangan Tarekat Khalwatiyah Samman di Sulawesi Selatan mulai terlihat sejak awal abad ke-19, ketika sekitar tahun 1820 M (1240 H) ajaran ini diperkenalkan melalui Syekh Abdullah al-Munir. Dari generasi inilah, Syekh Abdur Razak kemudian muncul sebagai penerus dan pemimpin yang mengakar di kalangan masyarakat Bugis. Ia membawa ajaran tarekat ini tidak sekadar sebagai ritual spiritual, melainkan sebagai sarana membangun harmoni sosial dan mempererat ikatan kultural.
Kisah hidup Syekh Abdur Razak juga diwarnai dengan perjalanan intelektual dan dakwahnya ke luar Sulawesi. Beberapa riwayat menyebut bahwa beliau pernah bermukim di Singapura, kemudian ke Pulau Sumbawa, khususnya di daerah Labu Bontong dan Jambu. Di sana, ia hidup sederhana, mengajar agama, serta membimbing masyarakat dalam amalan tarekat. Kehidupan di perantauan ini semakin meneguhkan posisinya sebagai seorang ulama yang membumi dan dekat dengan rakyat.
Namun, pada akhirnya Syekh Abdur Razak kembali ke tanah Bugis, tepatnya di Maros. Catatan sejarah menyebut bahwa pada tanggal 10 Sya’ban 1283 H, atau bertepatan dengan sekitar September–Oktober 1866 M, ia menetap di kampung Pacelle’, wilayah Turikale, Maros. Pemanggilan ini dilakukan dengan penghormatan penuh oleh bangsawan setempat, termasuk Karaeng Turikale, yang memandangnya sebagai ulama besar dengan kedudukan spiritual tinggi. Kepulangannya disambut dengan kebanggaan sekaligus harapan besar agar beliau menjadi pusat pengajaran agama dan tarekat.
Dalam kepemimpinannya, Syekh Abdur Razak menekankan prinsip kerendahan hati. Ia menolak untuk menjadikan tarekat sebagai organisasi dengan struktur formal. Baginya, otoritas spiritual tidak diukur dari jabatan administratif, melainkan dari maqam ruhani dan sanad keilmuan. Hal ini membuat Khalwatiyah Samman berkembang secara organik, melekat dalam keseharian masyarakat, dan tidak bergantung pada kekuasaan formal. Ajaran-ajarannya tersebar melalui murid-murid yang setia, yang kemudian menjadi tokoh penting di berbagai daerah.
Salah satu muridnya yang paling berpengaruh adalah Syekh Abdul Wahab Syamsul Arifin, yang lebih dikenal sebagai Puang Tuppu di Parengki, Maros. Melalui murid-murid seperti inilah, Tarekat Khalwatiyah Samman berkembang luas hingga ke Bone, Wajo, Sinjai, Mandar, dan wilayah lainnya di Sulawesi Selatan. Dengan demikian, Syekh Abdur Razak dapat dipandang sebagai simpul penting dalam jejaring tarekat yang membentuk wajah keagamaan masyarakat Bugis-Makassar.
Selain mengajarkan zikir, suluk, dan talqin, beliau juga berperan sebagai penengah dalam konflik sosial. Kehadirannya sering diminta untuk mendamaikan pertikaian antarwarga maupun antarbangsawan. Hal ini memperlihatkan bahwa ulama seperti Syekh Abdur Razak tidak hanya berfungsi sebagai guru spiritual, tetapi juga sebagai penjaga harmoni sosial dan budaya. Peran ganda ini menegaskan kedudukan ulama sebagai mediator antara agama dan tradisi lokal.
Menjelang akhir hayatnya, Syekh Abdur Razak menyerahkan ijazah tarekat kepada putranya, Syekh Abdullah bin Abdur Razak (dikenal sebagai Puang Ngatta). Peristiwa ini menandai kesinambungan ajaran tarekat dalam keluarga dan memastikan bahwa Khalwatiyah Samman tetap hidup di tengah masyarakat Bugis. Tidak lama setelah itu, sekitar tahun 1866 M, beliau wafat, meninggalkan warisan spiritual yang terus dikenang hingga kini.
Meskipun tidak banyak karya tulisnya yang tercatat, warisan Syekh Abdur Razak tetap hidup melalui murid-murid, tarekat, dan tradisi lisan masyarakat Bugis. Amalan-amalan zikir, suluk, dan pengajian tarekat yang masih berjalan hingga hari ini adalah bukti nyata pengaruhnya. Bahkan, di beberapa daerah, nama beliau masih disebut dengan penuh penghormatan sebagai seorang wali yang membawa kedamaian.
Dalam konteks sejarah Islam Nusantara, sosok seperti Syekh Abdur Razak membuktikan bahwa ulama lokal memiliki peran vital dalam mengakar kuatnya Islam di masyarakat. Mereka tidak hanya menyebarkan ajaran Islam, tetapi juga menyesuaikannya dengan falsafah budaya Bugis seperti siri’ na pacce, yang menekankan kehormatan dan solidaritas. Integrasi inilah yang menjadikan Islam diterima secara luas tanpa menimbulkan pertentangan dengan tradisi lokal.
Jejak Syekh Abdur Razak al-Buni Syams al-Arifin menunjukkan bahwa peradaban Islam di Sulawesi Selatan dibentuk bukan hanya oleh para penguasa atau bangsawan, tetapi juga oleh ulama tarekat yang membimbing masyarakat melalui ilmu, spiritualitas, dan keteladanan. Hingga kini, namanya tetap harum sebagai mursyid, guru, dan penjaga tradisi Islam Bugis, sekaligus teladan bahwa spiritualitas dapat membangun peradaban yang berakar kuat dalam budaya.
Oleh: Zaenuddin Endy
Wakil Ketua Lakpesdam NU Sulawesi Selatan 2024-2029