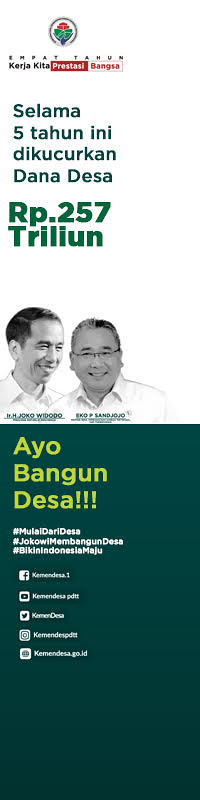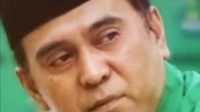Syekh Yusuf al-Makassari adalah salah satu ulama besar Nusantara yang meninggalkan pengaruh luas dalam sejarah Islam di Indonesia, bahkan hingga Afrika Selatan. Namun, warisan beliau tidak berhenti pada peran intelektual, sufistik, dan perjuangan melawan kolonialisme, tetapi juga terhubung melalui garis keturunan yang melanjutkan kiprahnya di Sulawesi Selatan. Dari pernikahannya dengan Ratu Aminah, putri Sultan Banten Ageng Tirtayasa, lahirlah seorang putra bernama Syekh Muhammad Maulana Jalaluddin. Tokoh ini menjadi simpul penting yang menghubungkan jalur genealogis ulama besar dengan elite politik di Sulawesi Selatan.
Dalam tradisi lisan dan dokumen genealogis, Syekh Muhammad Maulana Jalaluddin dikenal pula dengan sebutan Datu Bagusu Matowa atau Daengta ri Untiya. Gelar ini menunjukkan pengakuan masyarakat lokal terhadap kedudukan sosial dan spiritualnya. Kehadirannya tidak hanya mencerminkan kesinambungan darah dari seorang ulama besar, melainkan juga simbol keterhubungan antara pusat-pusat kekuasaan Islam di Jawa, Banten, dan Sulawesi Selatan. Dengan demikian, Jalaluddin menjadi figur pengikat antara spiritualitas dan politik.
Jejak historisnya semakin jelas ketika dikaitkan dengan garis keturunan Sunan Gunung Jati. Berdasarkan catatan silsilah, Jalaluddin disebut sebagai keturunan kedelapan dari Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga besar Syekh Yusuf bukan hanya berakar di Makassar, tetapi juga terkoneksi dengan tradisi penyebaran Islam di Jawa Barat dan Banten. Garis keturunan ini memperkuat legitimasi sosial dan religius keluarga besar Syekh Yusuf di mata masyarakat luas.
Dalam perkembangan selanjutnya, Syekh Muhammad Maulana Jalaluddin menikahkan anaknya, Bau Habibah atau Sitti Aisah, dengan La Temmassonge, Raja Bone ke-22. Perkawinan ini bukan sekadar urusan keluarga, tetapi juga strategi politik yang memperkuat hubungan antara keturunan ulama dan bangsawan. Di sinilah tampak jelas bagaimana warisan Syekh Yusuf bukan hanya dalam bentuk ajaran sufistik, melainkan juga dalam integrasi kekuasaan politik dengan legitimasi keagamaan.
Hubungan perkawinan itu melahirkan generasi yang berpengaruh dalam sejarah Bone dan Sulawesi Selatan. Dari garis ini kemudian muncul tokoh-tokoh yang berperan dalam menjaga warisan spiritual sekaligus memperkuat legitimasi politik. Keberadaan Jalaluddin menjadi titik penting dalam perjalanan sejarah Islam Bugis-Makassar, karena mampu mengikat jaringan kekuasaan antara kerajaan, ulama, dan masyarakat. Dengan demikian, perannya meneguhkan posisi keluarga Syekh Yusuf sebagai poros religius sekaligus politik.
Keberadaan Jalaluddin di Sulawesi Selatan juga menjadi bukti bahwa Islam tidak hanya disebarkan melalui dakwah atau perang, tetapi juga melalui perkawinan strategis. Perkawinan antara keluarga ulama dan bangsawan memperkuat penerimaan Islam dalam struktur sosial masyarakat Bugis-Makassar. Hal ini menjadi pola umum yang sering ditemukan dalam sejarah penyebaran Islam di Nusantara, di mana ulama besar masuk ke dalam lingkaran elite melalui pernikahan dan membentuk legitimasi yang kokoh.
Narasi genealogis ini banyak dipelihara melalui tradisi lisan, manuskrip lokal, serta catatan kerajaan. Meski terkadang muncul perdebatan tentang validitas detail silsilah, pengakuan masyarakat terhadap Jalaluddin sebagai keturunan Syekh Yusuf tetap kuat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya simbol genealogis dalam masyarakat Bugis-Makassar, di mana keturunan ulama dihormati bukan hanya karena darahnya, tetapi juga karena dianggap membawa keberkahan spiritual.
Selain itu, keberadaan Jalaluddin memperlihatkan keterhubungan trans-regional yang khas dalam sejarah Islam di Nusantara. Dari Makassar ke Banten, dari Banten ke Jawa Barat, lalu kembali ke Bone, garis keturunan ini menggambarkan jaringan ulama dan bangsawan yang melintasi batas geografis. Inilah yang menjadikan Islam di Nusantara begitu dinamis, karena dibangun melalui simpul-simpul yang menghubungkan berbagai wilayah.
Dalam perspektif sosiologis, figur Jalaluddin bisa dibaca sebagai representasi dari pola reproduksi sosial dan religius. Legitimasi keagamaan yang diwariskan dari Syekh Yusuf berpadu dengan kekuasaan politik kerajaan Bone. Hasilnya adalah struktur sosial yang lebih stabil, karena agama dan politik berjalan seiring. Hal ini juga memberi pengaruh pada cara masyarakat Bugis-Makassar menafsirkan hubungan antara ulama dan umara.
Jejak Jalaluddin juga tidak dapat dilepaskan dari konteks spiritualitas. Sebagai keturunan langsung dari seorang wali besar, keberadaannya senantiasa dikaitkan dengan keberkahan dan karomah. Masyarakat lokal melihat silsilahnya bukan hanya sebagai catatan sejarah, melainkan sebagai sumber legitimasi spiritual. Oleh karena itu, keturunan Jalaluddin banyak yang tetap dihormati hingga kini, baik di lingkaran pesantren, tarekat, maupun komunitas bangsawan.
Dari sisi historis, keberadaan Jalaluddin menunjukkan bagaimana dakwah Islam di Sulawesi Selatan bukan hanya persoalan penyebaran ajaran, tetapi juga integrasi sosial. Islam menjadi bagian dari struktur masyarakat, mengikat keluarga bangsawan dengan jaringan ulama. Hal ini memperlihatkan strategi yang lebih halus dan berkelanjutan dalam menyebarkan Islam, berbeda dengan narasi semata-mata tentang penaklukan atau peperangan.
Peran penting Jalaluddin ini juga masih terasa hingga generasi berikutnya. Banyak tokoh modern yang masih menelusuri garis keturunan hingga dirinya. Bahkan, silsilah ini disebut-sebut terhubung dengan beberapa tokoh publik masa kini. Hal ini menunjukkan bahwa genealogis ulama tetap memiliki daya tarik dan legitimasi, meskipun zaman sudah berubah.
Dari sudut pandang akademis, kisah Syekh Muhammad Maulana Jalaluddin mengajarkan kita pentingnya memahami sejarah melalui kombinasi tradisi lisan, manuskrip lokal, dan analisis kritis. Meski narasi genealogis sering kali bercampur dengan mitos, namun di dalamnya terkandung nilai tentang bagaimana masyarakat membangun identitas dan legitimasi. Kisah ini juga memperlihatkan bahwa warisan Syekh Yusuf tetap hidup, tidak hanya melalui ajaran tasawufnya, tetapi juga melalui garis keturunannya yang berkelindan dengan sejarah Sulawesi Selatan.
Dengan demikian, Syekh Muhammad Maulana Jalaluddin adalah figur kunci yang menjembatani warisan intelektual dan spiritual Syekh Yusuf dengan konteks politik dan sosial di Sulawesi Selatan. Jejaknya menghubungkan Banten, Jawa, dan Bone dalam satu garis sejarah yang kaya makna. Dari sini kita bisa memahami bahwa penyebaran Islam di Nusantara selalu menyatu antara dakwah, perkawinan, dan politik, membentuk jaringan sosial yang kuat dan berkelanjutan.
Oleh:Zaenuddin Endy
Wakil Ketua Lakpesdam NU Sulawesi Selatan 2024-2029