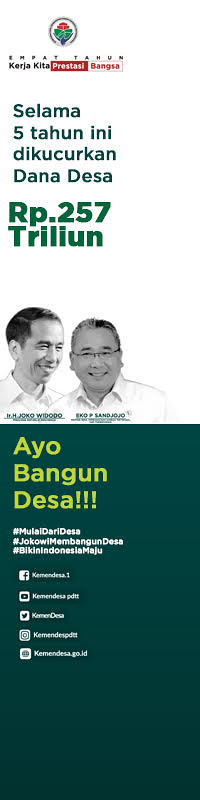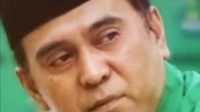Datuk Kalimbungan, yang bernama asli Syekh Muhammad Amir, merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah penyebaran Islam di wilayah selatan Sulawesi, khususnya di Bantaeng. Keberadaan beliau bukan sekadar legenda lokal, melainkan representasi dari dinamika islamisasi yang berlangsung seiring dengan arus dakwah yang dibawa oleh para ulama dari luar Sulawesi, terutama dari Minangkabau dan Aceh, yang diterima oleh kerajaan-kerajaan lokal, termasuk Kerajaan Gowa. Dalam sejarah lisan masyarakat Bantaeng, nama beliau dikenal sebagai Daeng Toa ri Kalimbungan, sosok yang memadukan kealiman, kesederhanaan, dan kharisma spiritual yang luar biasa.
Asal muasal Datuk Kalimbungan ditelusuri dari daerah Maiwa, Enrekang. Ia melakukan perjalanan dakwah ke selatan dan menetap di Kalimbungan, sebuah kawasan yang kini berada di Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng. Pemilihan lokasi tersebut bukan tanpa makna. Kalimbungan terletak di dataran yang sedikit tinggi, sekitar 35 meter di atas permukaan laut, dan menjadi titik pertemuan antara budaya lokal dan ajaran Islam yang dibawa sang datuk. Di tempat inilah, beliau mengembangkan dakwah dengan pendekatan sufistik dan kultural yang menyentuh aspek spiritual dan sosial masyarakat.
Jejak Syekh Muhammad Amir sebagai muballigh sangat menonjol. Ia bukan hanya dikenal sebagai pengajar ilmu agama, melainkan sebagai pembimbing rohani yang turut memengaruhi struktur keagamaan lokal. Ia dipercaya sebagai bagian dari mata rantai penyebar Islam di Sulawesi Selatan yang berafiliasi secara spiritual dengan pusat-pusat dakwah besar seperti Gowa dan Sumatera Barat. Tradisi pengajaran dan zikir yang ia bawa kemudian membentuk budaya keagamaan yang khas di Bantaeng. Dalam hal ini, beliau memainkan peran penting dalam peletakan syariat Islam secara kultural dan berkelanjutan.
Makam Datuk Kalimbungan kini menjadi situs penting bagi ziarah dan spiritualitas masyarakat. Terletak di tengah kampung Kalimbungan, makam ini tidak hanya menjadi tempat peristirahatan terakhir seorang ulama besar, tetapi juga simbol perpaduan antara tradisi lokal dan Islam. Peziarah yang datang tidak hanya berasal dari Bantaeng, tetapi juga dari berbagai daerah lain di Sulawesi. Di kompleks makam tersebut, ritual seperti pembakaran lilin, penyiraman minyak wangi, pembacaan doa, hingga penyembelihan hewan sesuai nazar, menjadi bagian dari tradisi yang dijaga secara turun-temurun.
Ritual “A’bunga ri Daeng Toa” merupakan salah satu praktik keagamaan yang berkembang di sekitar makam. Tradisi ini melibatkan ziarah, pelepasan ikatan nazar dalam bentuk tali plastik yang diikat di pohon, hingga berendam di sungai yang dianggap sakral. Bagi sebagian masyarakat, praktik ini mengandung makna spiritual yang dalam, meskipun juga mengundang perdebatan dari perspektif teologi Islam ortodoks. Beberapa ulama menilai praktik ini mendekati syirik, sementara yang lain melihatnya sebagai bentuk lokalitas religius yang telah terinternalisasi dalam budaya masyarakat secara kultural.
Dari perspektif sosiologis, situs makam Datuk Kalimbungan berfungsi sebagai ruang akulturasi antara Islam dan budaya lokal. Ia menjadi semacam “panggung spiritual” di mana nilai-nilai keislaman dilekatkan pada simbol-simbol tradisional. Dalam proses tersebut, lahirlah ekspresi religiositas yang khas dan kontekstual, tanpa kehilangan substansi teologis Islam. Tradisi ziarah, doa, serta penghormatan kepada tokoh agama semacam Datuk Kalimbungan menjadi bukti bagaimana Islam mampu beradaptasi dan mengakar dalam kehidupan masyarakat Bugis-Makassar.
Tak hanya berdampak secara spiritual dan sosial, keberadaan makam ini juga menumbuhkan geliat ekonomi mikro masyarakat sekitar. Pada hari-hari tertentu, seperti Maulid, Ramadhan, dan musim ziarah lainnya, masyarakat menjajakan perlengkapan ritual seperti bunga, minyak wangi, makanan, serta jasa pemandu lokal. Dalam konteks ini, tradisi ziarah tidak hanya memperkuat identitas religius, tetapi juga menjadi sumber penghidupan bagi sebagian warga.
Sebagai tokoh sejarah, Syekh Muhammad Amir atau Datuk Kalimbungan merupakan bukti bahwa proses islamisasi di Nusantara, khususnya Sulawesi Selatan, bukanlah peristiwa tunggal yang linear, melainkan hasil dari interaksi kompleks antara penyebar dakwah, masyarakat lokal, struktur kerajaan, serta nilai-nilai budaya setempat. Ia menjadi representasi dari ulama pembawa Islam yang tidak hanya berdakwah dengan lisan, tetapi juga dengan keteladanan hidup, kearifan lokal, dan pendekatan spiritual yang membumi.
Melalui jejak beliau, kita dapat mempelajari bagaimana Islam meresap secara damai ke dalam tatanan sosial dan budaya masyarakat Bugis-Makassar. Keteladanan Datuk Kalimbungan penting untuk dikaji lebih dalam, terutama dalam konteks pembangunan peradaban Islam lokal yang menghargai keberagaman ekspresi dan kearifan tradisional. Ia bukan sekadar figur sejarah, tetapi sumber inspirasi spiritual yang menegaskan bahwa Islam datang ke Nusantara bukan dengan pedang, melainkan dengan ilmu, cinta, dan budaya.
Oleh: Zaenuddin Endy
Koordinator Instruktur PKPNU Sulawesi Selatan