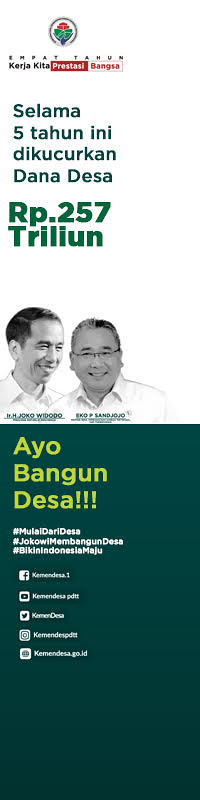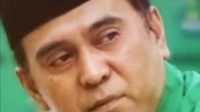Sejarah perjuangan rakyat Bone dalam menghadapi kolonialisme Belanda tidak hanya ditopang oleh kekuatan senjata dan strategi militer, tetapi juga oleh kekuatan spiritual, fatwa, dan kepemimpinan moral para ulama. Dalam konteks inilah dua sosok penting menonjol: KH. Muhammad Yusuf, Qadhi Bone ke‑13, dan Anreguru Semma Daeng Marola, seorang ulama dan bangsawan yang dikenal luas sebagai Arung Ponre. Keduanya menempati posisi strategis dalam membimbing umat dan masyarakat Bone menghadapi penjajahan dengan prinsip, keilmuan, dan keberanian.
KH. Muhammad Yusuf, sebagai Qadhi tertinggi Kerajaan Bone pada masa pemerintahan Raja ke‑31, La Pawawoi Karaéng Sigeri (1895–1905), adalah otoritas syar’i yang sangat disegani. Dalam masa-masa genting menjelang agresi militer Belanda ke wilayah Bone pada 1905, beliau mengeluarkan fatwa yang menjadi penentu arah sikap kerajaan dan umat Islam: menolak tunduk kepada kekuasaan kolonial, dan menganjurkan perlawanan sebagai bagian dari kewajiban agama. Fatwa ini membakar semangat rakyat, memperkuat legitimasi perjuangan, dan menjadikan KH. Yusuf sebagai tokoh sentral dalam narasi jihad melawan penindasan.
Sementara itu, Anreguru Semma Daeng Marola merupakan simbol pengabdian dan keteguhan di level lokal. Sebagai Arung Ponre dan ulama kharismatik, beliau tidak tinggal diam ketika Bone terancam pendudukan. Ia meninggalkan tanah kelahirannya dan bergabung bersama pasukan rakyat dalam barisan perlawanan. Tidak hanya itu, setelah perang usai dan Bone ditaklukkan secara militer, Anreguru Semma tetap teguh menjaga marwah pendidikan Islam di wilayah Bone. Ia menjadi guru utama bagi para bangsawan muda dan anak-anak elite Bone, memastikan bahwa nilai-nilai keberanian, keilmuan, dan spiritualitas tetap diwariskan.
Kedua tokoh ini, meskipun berbeda peran dan level pengaruh, menunjukkan satu hal yang sama: keberpihakan kepada umat dan prinsip keadilan. KH. Yusuf berdiri sebagai otoritas agama formal, penjaga hukum syariah dalam bingkai istana. Sedangkan Anreguru Semma berdiri di tengah masyarakat, menjadi jembatan antara elite kerajaan dan rakyat, antara nilai-nilai keislaman dan realitas sosial. Kolaborasi nilai yang mereka hadirkan membentuk semacam dwitunggal perjuangan Bone: hukum dan hikmah, fatwa dan keteladanan.
Menariknya, berdasarkan kesaksian turun-temurun dari beberapa keturunan mereka, KH. Muhammad Yusuf dan Anreguru Semma diyakini berasal dari satu garis keluarga. Bahkan dalam beberapa versi tutur lisan, keduanya disebut sebagai saudara kandung. Fakta ini, meski belum sepenuhnya terdokumentasi dalam naskah resmi kerajaan, memperkuat makna historis kebersamaan mereka sebagai bukan hanya rekan sejalan dalam perjuangan spiritual dan sosial, tetapi juga sebagai keluarga yang ditakdirkan menanggung amanah keulamaan bersama.
Fatwa yang dikeluarkan oleh KH. Muhammad Yusuf bukanlah sekadar pernyataan hukum agama, melainkan merupakan panggilan moral dan spiritual yang meresap dalam sanubari rakyat. Ia tidak sekadar menolak kolonialisme secara tekstual, tetapi menghidupkan kembali semangat siri’ dan pessé—nilai luhur masyarakat Bugis—sebagai dasar pembelaan terhadap agama dan tanah air. Hal ini memperlihatkan bagaimana syariat Islam dan kearifan lokal bertemu dalam satu semangat perjuangan yang autentik.
Anreguru Semma, sebagai representasi ulama lokal, membawa ruh Islam yang membumi. Ia tidak hanya dikenal sebagai ahli agama, tetapi juga sebagai pendidik dan pemimpin moral yang dihormati. Banyak tokoh muda Bone yang kelak menjadi pemimpin terinspirasi dari metode pendidikan dan keteladanan hidupnya. Ia menanamkan pentingnya beragama secara bijak, bersikap berani, dan berpegang pada etika keulamaan, sekaligus menghindari sikap ekstrem dan perpecahan di tengah masyarakat pasca-perang.
Keduanya juga menggambarkan dua bentuk ekspresi keulamaan di Sulawesi Selatan pada masa itu. KH. Muhammad Yusuf berperan dari dalam struktur istana dan kekuasaan formal, sementara Anreguru Semma dari luar tembok istana, hadir bersama rakyat, membangun dari bawah. Namun, keduanya tidak terpisah; mereka saling menguatkan dalam medan nilai dan visi perjuangan. Mereka menunjukkan bahwa perlawanan terhadap penjajah bisa dan harus berakar dari integritas ilmu dan keteladanan moral.
Yang menarik, nilai-nilai yang mereka wariskan tidak hanya relevan di masa lalu, tetapi tetap hidup hingga hari ini. Pesan moral, fatwa jihad, dan praktik pendidikan yang mereka kembangkan menjadi fondasi budaya Islam lokal yang bercirikan moderasi, kebangsaan, dan kecintaan terhadap kemerdekaan. Kisah-kisah mereka sebagai inspirasi perjuangan dan keteladanan spiritual masih membekas di masyarakat.
Dengan menelusuri jejak mereka, kita diajak untuk melihat bahwa perjuangan bukan hanya urusan senjata, melainkan juga urusan makna dan nilai. Bahwa kemenangan sejati bukan sekadar menaklukkan musuh di medan perang, tetapi menanamkan semangat kebenaran dan keteguhan dalam jiwa generasi sepanjang zaman. KH. Muhammad Yusuf dan Anreguru Semma telah menulis sejarah itu dengan tinta keteladanan, dan tugas kita hari ini adalah merawatnya dalam setiap langkah pengabdian pada umat dan bangsa.
Oleh: Zaenuddin Endy
Founder Komunitas Pecinta Indonesia dan Nusantara (KOPI-NU)