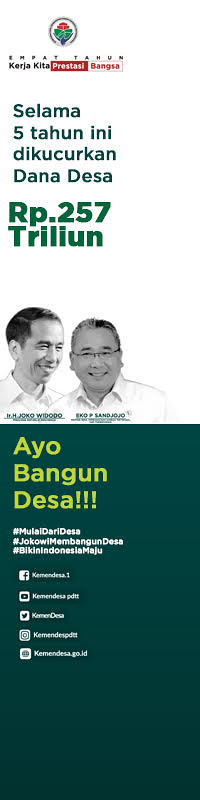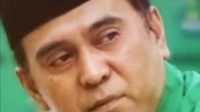Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), sebuah daerah yang membentang dari daratan hingga gugusan pulau di pesisir barat Sulawesi Selatan, menyimpan jejak panjang peradaban Islam yang tak hanya terpatri dalam masjid dan pesantren, tetapi juga dalam keteladanan ulama yang menjadi tonggak utama transmisi ilmu dan nilai-nilai spiritual masyarakat setempat. Menelusuri jejak para ulama di Pangkep sama artinya dengan mengungkap lapis-lapis sejarah dakwah Islam yang berpijak pada tradisi, tarekat, dan keilmuan klasik yang terus hidup hingga hari ini.
Salah satu kawasan yang memiliki jejak keulamaan paling kuat di Pangkep adalah Pulau Salemo, yang bahkan dijuluki sebagai “Pulau Ulama.” Sejak awal abad ke-20, pulau ini menjadi pusat pembelajaran Islam, tempat berkumpulnya para guru agama dan santri dari berbagai penjuru. Ulama-ulama seperti Syekh Muhammad Shiddiq (1830–1937) muncul sebagai figur sentral. Ia merupakan cucu KH Sibbawaih yang memiliki garis keilmuan dari Makkah dan mendirikan pusat pengajian di Rappokadang dan Kabba. Sosok ini menjadi rujukan spiritual tidak hanya bagi masyarakat biasa, tapi juga bangsawan seperti Andi Mappanyukki dari Kerajaan Bone.
Kehadiran ulama seperti Syekh Muhammad Shiddiq menunjukkan bahwa dakwah Islam di Pangkep sejak awal telah berpijak pada otoritas keilmuan yang bersambung langsung dengan pusat-pusat ilmu Islam klasik. Ulama tidak hanya berfungsi sebagai pengajar agama, tetapi juga sebagai penjaga nilai dan penuntun moral dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Tradisi halaqah, musyawarah, dan pengajian rutin menjadi bagian tak terpisahkan dari aktivitas keseharian mereka.
Dinamika ulama di Pangkep tidak terlepas dari jaringan tarekat, terutama Khalwatiyah Yusufiyah. Tarekat ini berkembang pesat di daerah pesisir dan kepulauan Pangkep, dibawa oleh para mursyid seperti Syekh Abdul Rahim al-Hafidz (Puang Awalli) dan dilanjutkan oleh murid-muridnya seperti Syekh Zainuddin Assegaf, Sayyid Muhammad Shaleh, dan Puang Ramma. Tarekat ini bukan hanya menyebarkan dzikir dan wirid, tetapi juga memperkuat karakter sosial dan moral masyarakat pesisir yang berinteraksi dengan dunia maritim dan perdagangan.
Khalwatiyah Yusufiyah bukan semata tarekat spiritual, tetapi juga jaringan sosial yang menyatukan masyarakat dalam prinsip egaliter dan disiplin batin. Dalam masyarakat Pangkep, terutama di wilayah pulau-pulau, ajaran tarekat ini membentuk etos kesalehan kolektif yang membentengi komunitas dari pengaruh eksternal yang destruktif. Kepatuhan kepada mursyid, kedekatan dengan alam, dan sikap hidup bersahaja menjadi ciri utama komunitas tarekat ini.
Nama-nama ulama seperti AGH Abdurrahim (Cella’ Panrita), AGH Paharuddin, AGH Muhammad Said Maulana, dan AGH Abdul Gaffar (Puang Tobo) juga tercatat dalam lintasan sejarah Islam lokal. Mereka bukan hanya pengajar kitab kuning, tetapi juga penggerak sosial yang mendirikan masjid, lembaga pendidikan, dan menghubungkan masyarakat dengan pesantren-pesantren besar di Gowa, Bone, dan Soppeng. Dari tangan mereka lahir generasi intelektual yang tak hanya memahami agama, tetapi juga aktif dalam pembangunan masyarakat.
AGH Abdurrahim, misalnya, dikenal luas sebagai ulama sekaligus penasihat spiritual masyarakat nelayan. Di balik kesahajaan hidupnya, beliau adalah penjaga tradisi lisan dan penghubung budaya Bugis dengan nilai-nilai Islam. Kecakapannya dalam mengurai makna kitab kuning maupun hikmah sufistik menjadikannya rujukan utama dalam banyak musyawarah adat dan agama.
Tradisi pengajian di surau dan langgar kecil yang tersebar di kampung-kampung menjadi sarana utama transformasi keislaman di Pangkep. Di tempat-tempat sederhana itulah, santri belajar membaca kitab kuning, memahami tata cara ibadah, dan mempraktikkan ajaran akhlak mulia. Para ulama berperan ganda, sebagai pendidik dan penjaga harmoni sosial di tengah masyarakat yang majemuk secara ekonomi dan budaya.
Menariknya, jejak intelektual ulama Pangkep juga menyebar lewat lisan dan manuskrip. Banyak dari mereka adalah penulis syair-syair keislaman dalam aksara lontaraq dan Arab-Melayu, yang menjadi bagian dari khazanah sastra Islam Bugis. Tradisi ini memperlihatkan bahwa Islam di Pangkep bukanlah sesuatu yang kaku, melainkan cair dan menyatu dengan ekspresi budaya lokal.
Sastra Islam lokal yang hidup di Pangkep menandai pertemuan antara wahyu dan warisan leluhur. Dalam bait-bait syair tersebut, terkandung ajaran tauhid, kisah nabi, dan tuntunan etika yang dikemas dalam bahasa yang lembut, simbolik, dan penuh nuansa lokal. Hal ini memperlihatkan kemampuan ulama dalam mengadaptasi Islam dalam wadah budaya yang telah mapan tanpa kehilangan esensi ajaran Islam itu sendiri.
Di antara manuskrip yang pernah ditulis dan diwariskan turun-temurun adalah tafsir sederhana dalam bahasa Bugis, kumpulan hadis tentang akhlak, hingga risalah-risalah tarekat yang ditulis dalam aksara lontaraq. Naskah-naskah ini menjadi saksi bisu peran intelektual para ulama yang tidak hanya berdakwah dengan lisan, tetapi juga dengan tulisan yang mendalam dan penuh kearifan.
Dalam konteks kekinian, warisan para ulama tersebut menjadi tantangan tersendiri. Modernisasi dan digitalisasi membawa perubahan dalam cara masyarakat mengakses ilmu dan nilai. Namun, keteladanan ulama Pangkep tetap relevan, terutama dalam aspek pendidikan karakter, spiritualitas, dan keberagamaan yang moderat. Upaya pelestarian manuskrip dan biografi para ulama menjadi bagian penting dari penguatan identitas keislaman lokal.
Beberapa pesantren di Pangkep kini mulai menghidupkan kembali tradisi intelektual dan spiritual para pendahulu. Santri diajak untuk tidak hanya mempelajari fiqh dan nahwu, tetapi juga memahami sejarah lokal, tarekat, dan kesusastraan Islam Bugis. Kegiatan ini diharapkan mampu melahirkan generasi baru yang tidak tercerabut dari akar budaya dan nilai-nilai spiritual nenek moyang mereka.
Kegiatan seperti ziarah ke makam para ulama, pengajian haul, dan pembacaan syair-syair Bugis Islami menjadi bagian dari revitalisasi kultural yang melibatkan komunitas secara luas. Di sinilah agama bukan sekadar doktrin, tetapi pengalaman kultural yang menyentuh hati dan menguatkan relasi sosial. Islam yang hidup di Pangkep adalah Islam yang merangkul, bukan menghakimi.
Jejak ulama di Pangkep juga membentuk tradisi kepemimpinan keagamaan yang kuat. Para imam masjid, khatib Jumat, dan guru ngaji di desa-desa masih memegang garis keilmuan dari para ulama besar terdahulu. Keberlanjutan ini memperlihatkan kesinambungan sanad keilmuan yang dijaga dengan penuh tanggung jawab.
Selain itu, posisi ulama di Pangkep sering kali beriringan dengan tokoh adat. Keduanya menjadi poros pengayom masyarakat, menjaga keseimbangan antara hukum agama dan norma sosial. Dalam banyak kasus, penyelesaian konflik sosial diserahkan kepada hikmah kolektif para panrita (cendekiawan adat dan agama), yang berangkat dari nilai-nilai Islam dan kearifan lokal.
Merekam jejak ulama di Pangkep sejatinya adalah merekam denyut nadi spiritualitas Bugis yang hidup dalam keseharian. Di balik wajah-wajah bersahaja para guru ngaji dan mursyid tarekat itu, tersimpan warisan besar yang tak ternilai: akhlak, ilmu, dan keteguhan dalam mengabdi pada umat dan agama. Warisan ini patut diabadikan, bukan hanya dalam tulisan, tetapi juga dalam praktik kehidupan kita sehari-hari.
Sebagaimana laut dan pulau-pulau Pangkep yang tak henti bergelombang, demikian pula jejak ulama yang terus mengalir dalam ingatan kolektif masyarakatnya. Meski zaman berganti, nilai-nilai yang ditanamkan mereka tetap hidup—membentuk cara berpikir, bersikap, dan bermasyarakat. Dari Salemo hingga daratan Pangkep, dari pengajian kecil hingga pesantren besar, warisan ini adalah denyut jantung keislaman lokal yang tak boleh padam.
Oleh: Zaenuddin Endy
Koordinator Instruktur PKPNU Sulawesi Selatan